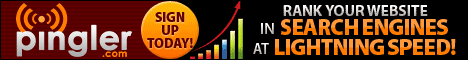Cara Pengolahan Sampah dan Metode Pengolahan Sampah
Secara umum, proses teknologi pada IPST SARBAGITA dapat dijelaskan, yaitu
1.Pemisahan Awal
Agar proses konversi energi sampah dapat berjalan baik, maka dilakukan pemisahan sampah dalam kategori sebagai berikut:
•Sampah organik bio-degradasi (baik basah maupun kering), contoh: sampah buah-buahan, dan sampah sayuran;
Sampah organik yang diproses di IPST SARBAGITA umumnya berasal dari sampah rumah tangga, kompleks perumahan, dan pasar-pasar tradisional. Sampah-sampah organik ini dikumpulkan untuk selanjutnya akan diangkut oleh truk-truk pengangkut sampah yang memang bertugas untuk mengangkut sampah-sampah organik ini yang kemudian akan dibawa ke TPA Suwung dan kemudian diproses di IPST SARBAGITA.
•Sampah organik non-biodegradasi (baik basah maupun kering), contoh: plastik dan kayu;
Pihak pengelola TPA Suwung dan IPST SARBAGITA juga melakukan kerjasama dengan para pemulung untuk membantu mengumpulkan sampah-sampah non-organik, khususnya sampah plastik. Pihak pengelola TPA Suwung dan IPST SARBAGITA menyediakan tempat khusus bagi para pemulung untuk mengumpulkan dan memilah sampah-sampah yang mereka dapatkan. Pihak pengelola juga menyediakan truk-truk pengangkut sampah yang juga dapat mengangkut sampah nonorganik.
•Sampah inert, contoh: besi, kaca, sisa bahan bangunan
Setelah dilakukan pemisahan diatas, maka sampah selanjutnya dimasukkan ke dalam mesin pencacah (shreder) untuk menyaring dan memisahkan sampah beradasarkan ukurannya. Proses ini dilaksanakan di dalam bangunan MRF (Material Recycle Facility).
2.Landfill Gas
Landfill adalah suatu proses pengambilan gas methan dari tumpukan sampah lama (landfilling). Tumpukan sampah lama ditutup dengan lapisan tanah untuk menghindari lepasnya gas methan yang sangat berbahaya bagi lingkungan (karena gas ini mudah terbakar). Selanjutnya, jaringan pipa gas perforasi dimasukkan ke dalam tumpukan sampah untuk menyedot gas methan menuju fasilitas gas treatment.
3.Proses Anaerobis Diggestion
Proses Anaerobic Diggestion, maka dilakukan untuk pengelolaan sampah basah pada structured landfill dengan melibatkan bakteri, yaitu bakteri EM4 yang tipenya sama dengan bakteri yang menghasilkan landfill gas dan sewage gas. Bakteri ini juga berfungsi untuk mengurangi bau bususk yang ditimbulkan oleh sampah Penguraian oleh bakteri biasanya akan menghasilkan bio gas dan membutuhkan waktu antara 1 sampai 2 minggu serta kontrol yang baik untuk menjamin kesempurnaan proses sanitasi. Sisa padat dari proses ini dapat digunakan sebagai bahan baku pupuku berkualitas tinggi dengan menerapkan teknologi pengolahan kompos lanjutan. Sedangkan sisa air hasil proses dapat diolah kembali atau langsung disalurkan kembali ke awal proses. Dengan teknologi ini, maka volume sampah dapat berkurang menjadi 10%-15% dari volume awal.
4.Gasifikasi dan Pyrolisis
Gasifikasi adalah proses dekomposisi termal dari bahan organik dengan mengurangi keberadaan oksigen. Gasifikasi dan Pyrolisis merupakan proses yang pemanasannya dilakukan dengan suhu, bukan dengan api dan dilakukan dalam ruang hampa. Proses ini dapat mengubah sampah organik kering menjadi synthetic gas (karbon monoksida dan hidrogen) dalam sebuah gasifier yang kemudian dapat dipakai untuk menggerakkan gas engine sebagai mesin pembangkit listrik. Gasifier pada dasarnya bukanlah teknologi baru karena sudah diterapkan secara komersil di Inggris selama 10 tahun. Gasifikasi juga merupakan proses penghancuran tampak dengan energi panas 1300oC yang dilakukan dalam ruang hampa, jadi tidak menggunakan oksigen. Yang perlu diingat pada proses ini bukanlah pembakaran, tetapi pemanasan sampai sampah itu berubah menjadi gas dan abu. Dalam proses ini sampah akan direduksi sebanyak 55 – 98%, kemudian hasil pemanasannya akan menjadi gas dan abu. Gasnya akan ditangkap semua dan akan diolah menjadi listrik. Listrik yang dihasilkan tergantung volume sampah dan akan dijual ke Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang kebetulan sedang kekurangan listrik atau kekurangan daya listrik. Kemudian abunya dapat dibuat menjadi berbagai macam bahan baku, seperti bahan baku yang sangat bagus untuk membuat aspal, karena kandungan karbonnya yang tinggi. Namun, abu ini harus dicampur dengan zat yang lain untuk menghasilkan aspal yang berkualitas.
5.Hasil Pengolahan dan Produk IPST
Dengan seluruh proses di atas maka volume sampah dapat berkurang sampai 80%. Gas yang dihasilkan (biogas gas, methane gas, dan synthetic gas) selanjutnya akan diproses pada fasilitas gas treatment untuk dapat menjadi bahan bakar (gas engine) mesin pembangkit listrik
6.Kualitas Emisi Gas Buang
Buangan gas dengan teknologi ini memiliki emisi yang sangat rendah dan ramah lingkungan. Buangan gas ini memiliki emisi yang rendah karena telah mengalami berbagai macam proses penyaringan dan pengurangan emisi.
Dengan IPST, maka sampah yang ada di TPA Suwung, baik sampah baru maupun sampah lama akan diolah melalui teknologi GALFAD (Gasifikasi, Landfill, dan Anaerobic Digestion) menjadi listrik (energi) dan produk-produk lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat dan memberikan kontribusi ekonomi bagi kedua belah pihak. Untuk menjaga hubungan dengan masyarakat sekitar, maka Pemda SARBAGITA dan Swasta berkomitmen untuk meningkatkan kualitas lingkungan sekitarnya dengan mengembangkan dan melaksanakan program rehabilitasi dan pelestarian lingkungan yang melibatkan masyarakat sekitar. Upaya pemberdayaan masyarakat sekitar juga dilakukan dengan adanya komitmen bersama dengan memberikan kesempatan kerja kepada penduduk sekitarnya untuk menjadi tenaga operasional sesuai kemampuan persyaratan teknis yang diperlukan. Dalam hal ini, mitra swasta juga memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan alih teknologi kepada tenaga kerja lokal sepanjang persyaratan pendidikan dan teknis memungkinkan. Berbagai upaya diatas merupakan upaya bersama untuk membangun sinergi antar pemerintah, swasta, masyarakat, dan lingkungan sehingga IPST dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan berkelanjutan.
Untuk menunjang operasional pengolahan sampah, maka IPST SARBAGITA memiliki sejumlah fasilitas-fasilitas. IPST SARBAGITA memiliki kantor administrasi yang terletak di TPA Suwung. Kantor administrasi ini berfungsi sebagai tempat pemantauan utama kegiatan yang dilaksanakan di IPST SARBAGITA dan juga sebagai sumber informasi bagi masyarakat umum yang ingin mengetahui berbagai macam hal mengenai IPST SARBAGITA. Selain kantor administrasi yang bertempat di TPA Suwung, pihak pengelola IPST SARBAGITA, yaitu Badan Pengelola Kebersihan SARBAGITA (BPKS) juga memiliki kantor di Gedung III Lantai 3 Bappeda Provinsi Bali, Jl. Kapten Cok Agung Tresna, Niti Mandala Renon, Denpasar-Bali. Untuk proses pemilahan dan pengolahan sampah, IPST SARBAGITA memiliki berbagai macam fasilitas-fasilitas misalnya, infrastruktur seperti jalan, jembatan timbang, ruang pembilahan, cell landfill, ruangan konversi gas dan listrik, buffer untuk sampah, ruang pengeringan/ ruang untuk penyerakan sampah, dan lain – lain. Sebagian besar dari fasilitas pengolahan dan pemilahan sampah ini masih milik investor pembangun IPST SARBAGITA, yaitu PT. Navigat Organic Energi Indonesia (PT. NOEI).
Alat - alat yang digunakan untuk konversi listrik dan pembilahan menggunakan teknologi, seperti semi teknologi. Teknologi ini dilakukan dengan memasukkan sampah dalam roda berjalan yang kemudian akan diambil oleh sekitar 60 orang pekerja untuk dipilah atau diambil, ada yang mengambil plastik, kaleng, kaca, dan lain – lain. Teknologi yang digunakan adalah semi teknologi dan multimedia yaitu sampah yang tidak diambil akan terus lanjut sampai ke cell landfill yang berupa kumpulan sampah organik. Setelah penuh, sampah-sampah tersebut akan ditutup dengan membrane. Di IPST SARBAGITA ini tersedia 11 cell, misalnya cell 1 sudah penuh kemudian dilanjutkan ke cell 2, dan seterusnya. Untuk memenuhkan 1 cell kira-kira butuh waktu 1 bulan.
Tenaga operasional atau tenaga kerja di IPST SARBAGITA dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tenaga kerja tanpa keterampilan khusus dan tenaga kerja dengan keterampilan khusus. Tenaga kerja tanpa keterampilan khusus ini diambil dari masyarakat lokal yang bertugas untuk memungut dan memilah sampah-sampah yang selanjutnya akan diproses. Untuk tenaga kerja dengan keterampilah khusus, umumnya direkrut untuk menjadi teknisi, misalnya teknisi pengoperasian alat, teknisi untuk mengolah kandungan-kandungan kimia, dan teknisi pengawasan proses pemilahan pengolahan sampah.
Total sampah yang memenuhi area TPA Suwung saat ini mencapai 40 Ha yang merupakan sampah dari tahun 1990, sedangkan yang digunakan untuk IPST SARBAGITA hanya 10 Ha. Untuk menanggulangi sisa sebesar 30 Ha, investor rencananya akan membangun IPST baru guna mengolah sampah sebesar 30 Ha ini. Yang sudah dibangun yaitu ruang pembilahan.
Pengoperasian IPST SARBAGITA diujicoba pertama kali sekaligus peresmiannya (soft opening) pada tanggal 13 Desember 2007 oleh Bapak Gubernur Bali bertepatan dengan diadakannya Konferensi PBB mengenai pemanasan global (UNFCCC) di Nusa Dua. Sekaligus juga sebagai pembuktian proyek CDM (Clean Development Mechanism) pertama di Indonesia yang teregistrasi di PBB pada tanggal 20 Mei 2007. Keberhasilan dan penerapan teknologi pengolahan sampah pada IPST SARBAGITA tersebut akan sangat tergantung dari dukungan semua pihak, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Manfaat Pembangunan IPST SARBAGITA
Pembangunan IPST SARBAGITA di TPA Suwung memberikan banyak manfaat tidak hanya bagi kebersihan lingkungan, tetapi juga pembangunan IPST SARBAGITA dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Sebelum dibangunnya IPST SARBAGITA, sampah-sampah yang berasal dari daerah SARBAGITA (Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan) ditumpuk begitu saja di TPA Suwung. Ini menyebabkan lahan TPA Suwung habis dipergunakan sebagai tempat penumpukan sampah tanpa adanya proses pengolahan sampah lebih lanjut. Jika hal seperti ini terus terjadi, dikhawatirkan lahan di TPA Suwung nantinya tidak dapat menampung sampah lagi. Menurut Bapak Ir. Kadek Agus Adiana, MM selaku Kepala Bidang Pengembangan Usaha Badan Pengelola Kebersihan SARBAGITA (Kabid Pengembangan Usaha BPKS SARBAGITA), adanya pengolahan sampah di IPST SARBAGITA dapat memberikan manfaat, yaitu memperpanjang usia lahan di TPA Suwung. Jika sampah ditumpuk begitu saja tanpa adanya proses pengolahan sampah lebih lanjut, lahan yang dipergunakan untuk tempat penumpukan sampah akan mengalami proses pencemaran akibat air-air sampah yang masuk ke dalam tanah. Air-air sampah ini akan terbentuk bila sampah ditumpuk terlalu lama. Belum lagi tumpukan sampah dapat menimbulkan bau yang tidak enak jika tidak cepat dilakukan proses pengolahan sampah lebih lanjut. Pengolahan sampah yang dilakukan di IPST SARBAGITA dapat memperpanjang usia lahan di TPA Suwung karena sampah tidak mengalami proses penumpukan yang lama dan cepat dapat diolah, sehingga air-air sampah dan bau yang tidak enak dapat diminimalkan jumlahnya. Selain dapat memperpanjang usia lahan di TPA Suwung, pembangunan IPST SARBAGITA juga dapat memberikan kontribusi dalam bidang ekonomi. Hasil-hasil pengolahan sampah di IPST SARBAGITA yang sebagian besar hasil pengolahannya dalam bentuk listrik dapat dijadikan salah satu sumber pendapatan ekonomi. Hasil-hasil pengolahan sampah lainnya dalam bentuk pupuk dan dalam bentuk abu sebagai salah satu bahan baku pembuatan aspal karena memiliki kadar karbon yang tinggi juga dapat dijadikan produk untuk memberikan pendapatan ekonomis.
Selain bermanfaat untuk lingkungan dan memberikan pendapatan ekonomis, pembangunan IPST SARBAGITA juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar yang tinggal di sekitar TPA Suwung. Masyarakat yang tidak memiliki kemampuan khusus diberikan kesempatan untuk bekerja sebagai tenaga kerja di IPST SARBAGITA. Masyarakat yang dulunya tidak memiliki sumber penghasilan tetap, kini memiliki penghasilan tetap akibat adanya pembangunan IPST SARBAGITA.
Pihak pengelola IPST SARBAGITA dan investor pembangunan IPST SARBAGITA, yaitu PT. Navigat Organic Energy Indonesia (PT. NOEI) berkomitmen untuk tetap menjaga kelestarian hutan bakau yang terdapat di sekitar IPST SARBAGITA dan TPA Suwung. Komitmen ini dilakukan untuk tetap menjaga ekosistem laut dan satwa-satwa yang hidup di sekitar hutan bakau. Proses pengolahan sampah yang dilakukan di IPST SARBAGITA dilakukan sedemikian rupa agar hasil-hasil pengolahan sampah tidak mencemari hutan bakau dan ekosistemnya. Komitmen pengelolaan hutan bakau ini juga berlaku untuk pengelolaan sampah di TPA Suwung.
Sabtu, 02 Oktober 2010
Jumat, 24 September 2010
Berwisata ke Tempat Pengolahan Sampah di Osaka Jepang
Tempat Pengolahan Sampah (TPS) adalah senjata terakhir pemerintah kota dalam mengelola sampah kotanya, namun hingga kini TPS-bagi masyarakat-bukan sesuatu yang layak dikenal.
Citra TPS sebagai tempat yang kotor dan-sangat mungkin-menjadi sumber penyakit menjadikan penolakan warga akan keberadaan TPS di lingkungannya menjadi dapat dimengerti. Keberadaan teknologi yang menjamin sistem pengolahan sampah yang bersih dan aman, tidak dapat dipungkiri menjadi salah satu solusi yang harus bisa disosialisasikan kepada masyarakat. Namun di samping itu, tampilan fisik dan program ruang sebuah TPS juga dapat merubah citra buruknya di mata masyarakat. Untuk itu, beberapa kota dunia-seperti New York, Paris, dan Vienna-memanfaatkan kemampuan arsitektur untuk memperbaiki citra sekaligus merubah persepsi masyarakat terhadap tempat pengolahan limbah tersebut. Jepang-salah satu negara maju yang menerapkan aturan ketat mengenai sampah-juga memiliki Naka Waste Incineration Plant di Hiroshima dan Maishima Incineration Plant di Osaka yang dapat dijadikan contoh usaha tersebut.
Kedua fasilitas Incineration Plant ini selesai dibangun tahun 2004 (Hirsohima) dan 2001 (Osaka) untuk melengkapi fasilitas pengolahan sampah di masing-masing kota. Pada kedua fasilitas ini, tampilan fisik benar-benar berhasil “menipu” persepsi masyakarat tentang fungsi yang bekerja di dalamnya. Citra arsitektur kontemporer dengan bentuk asimetris-geometris, non-dekoratif, dan metal sebagai kulit bangunan Hiroshima Naka Waste Incineration Plant menimbulkan citra bangunan yang megah, bersih dan formal yang sangat bertolak belakang dengan citra fasilitas pengolahan limbah selama ini. Yoshio Taniguchi, arsitek yang sangat terkenal dengan desain-desain museumnya-termasuk Museum of Modern Art (MoMA) New York-bahkan dengan bangga menyebut Hiroshima Naka Waste Incineration Plant sebagai desain “museum of garbage“nya. Pendekatan yang sama, namun dengan eksekusi yang berbeda terlihat di Osaka City Environmental Management Bureau’s Maishima Incineration and Water Treatment Plants, yang didesain oleh arsitek konservasi lingkungan terkenal dari Austria, Meister Friedensreich Hundertwasser. Fasilitas pengolahan sampah ini tampil bagai lukisan di atas kanvas sehingga lebih layak diduga sebagai theme park. Bentuk bangunan yang lebih dinamis, material yang sangat bervariasi, permainan bentuk dan warna pada elemen-elemen bangunan (jendela, pintu, langit-langit) serta penghijuan berhasil menyampaikan pesan positif “the harmony between ecology, technology, and art” yang ingin disampaikan oleh arsitek melalui fasilitas ini. Namun, kedua fasilitas ini menjadi lebih istimewa karena memang dibangun untuk memberikan “pelayanan” kepada masyarakat dan menjadi bagian dari masyarakat.
Fungsi publik dalam fasilitas pengolahan limbah
Usaha awal yang dilakukan pemerintah kota Hiroshima dan Osaka adalah dengan memasukkan fungsi incineration plant ini kedalam visi dan misi serta rencana infrastruktur pembangunan kawasan atau kota. Hiroshima Naka Incineration Plant tidak lain adalah bagian dari rencana kota Hiroshima untuk membangun infrastruktur-infrakruktur sosial kota sebagai bagian dari proyek “Hiroshima 2045: the city of Peace and Creation” sekaligus memperkuat tema “The Water City Hiroshima.“ Begitu juga Osaka Maishima Incineration Plant-yang berada tepat di pintu masuk pulau buatan ini-tidak lain adalah bagian penting dari masterplan kawasan Maishima sebagai “Maishima Sports Island” dan juga pendukung kota Osaka untuk memenangkan persaingan sebagai tuan rumah Olympiade Musim Panas 2008-yang direncanakan berpusat di pulau Maishima tersebut-saat itu.
Bangunan Hiroshima Naka Incineration Plant yang terdiri dari 1 lantai basement, 7 lantai kantor pengelola dan 1 lantai penthouse hanya menempati 27 persen dari luas total tapak sebesar 50,200m2, sementara sisanya didedikasikan bagi masyarakat dan kota Hiroshima dalam wujud waterfront park. Bangunan tersebut dibagi menjadi tiga zona oleh Taniguchi, dimana salah satu zona yang berada di bagian tengah disulap sebagai zona publik. Zona publik yang terdiri dari atrium dan dikelilingi oleh koridor viewing gallery ini memungkinkan masyarakat dapat melihat isi dari “perut” incinerator ini, serta pemandangan laut, pelabuhan dan kota Hiroshima. Kemudian, Taniguchi menempatkan walkway ecorium sepanjang 400 kaki menembus atrium tersebut. Ecorium ini memiliki fungsi istimewa sebagai media informasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui urutan proses dan teknologi pengolahan yang dimiliki; menghubungkan pemukiman dengan waterfront park baru yang berada di sisi selatan bangunan; dan juga memainkan peran simbolik sebagai gerbang yang menghubungkan laut dengan kota Hiroshima. Terakhir, fungsi ekologis fasilitas bagi kota dan kawasan sekitarnya ini dipertegas dengan ditanaminya pepohonan disekeliling bangunan dan juga di dalam atrium.
Begitu pula bangunan 7 lantai Osaka Maishima Incineration Plant membuka dirinya untuk masyarakat yang ingin mengetahui fasilitas pengolahan sampah ini sekaligus belajar mengenai manajeman pengolahan sampah kota Osaka. Masyarakat hanya perlu mendaftarkan diri satu minggu sebelumnya untuk mengikuti tour tersebut. Bangunan juga dibagi ke dalam 3 zona, dan Hundertwasser meletakkan lobby dan visitor observation deck di bagian tengah bangunan untuk memberi kesempatan bagi pengunjung melihat sebagian proses pengolah sampah berteknologi tinggi tersebut dan membuktikan bahwa sebuah TPS bisa menjadi tempat yang sangat bersih, indah dan berkesan modern. Dari luar, mosaic keramik, dan bentuk organis serta warna-warni semua elemen bangunan menjadi strategi tersendiri untuk mempercantik kawasan ini. Proses pendataan setiap truk-truk sampah yang masuk dan keluar fasilitas ini juga bisa disaksikan masyarakat dari luar bangunan. Fasilitas ini tidak luput dari unsur penghijauan yang berada di taman-taman yang mengelilinginya, di atap bangunan serta pohon-pohon yang menjulur keluar dari jendela-jendela bangunan.
Apa yang dilakukan oleh kedua fasilitas ini adalah mendekatkan diri kepada masyarakat dan membawa masyarakat menjadi satu bagian dari fasilitas dan permasalahan sampah kota, sehingga dengan menginformasikan proses pengolahan sampah, produksi sampah setiap hari nya, diharapkan mampu membuat masyarakat lebih sadar dalam mengelolah sampah nya.
Citra TPS sebagai tempat yang kotor dan-sangat mungkin-menjadi sumber penyakit menjadikan penolakan warga akan keberadaan TPS di lingkungannya menjadi dapat dimengerti. Keberadaan teknologi yang menjamin sistem pengolahan sampah yang bersih dan aman, tidak dapat dipungkiri menjadi salah satu solusi yang harus bisa disosialisasikan kepada masyarakat. Namun di samping itu, tampilan fisik dan program ruang sebuah TPS juga dapat merubah citra buruknya di mata masyarakat. Untuk itu, beberapa kota dunia-seperti New York, Paris, dan Vienna-memanfaatkan kemampuan arsitektur untuk memperbaiki citra sekaligus merubah persepsi masyarakat terhadap tempat pengolahan limbah tersebut. Jepang-salah satu negara maju yang menerapkan aturan ketat mengenai sampah-juga memiliki Naka Waste Incineration Plant di Hiroshima dan Maishima Incineration Plant di Osaka yang dapat dijadikan contoh usaha tersebut.
Kedua fasilitas Incineration Plant ini selesai dibangun tahun 2004 (Hirsohima) dan 2001 (Osaka) untuk melengkapi fasilitas pengolahan sampah di masing-masing kota. Pada kedua fasilitas ini, tampilan fisik benar-benar berhasil “menipu” persepsi masyakarat tentang fungsi yang bekerja di dalamnya. Citra arsitektur kontemporer dengan bentuk asimetris-geometris, non-dekoratif, dan metal sebagai kulit bangunan Hiroshima Naka Waste Incineration Plant menimbulkan citra bangunan yang megah, bersih dan formal yang sangat bertolak belakang dengan citra fasilitas pengolahan limbah selama ini. Yoshio Taniguchi, arsitek yang sangat terkenal dengan desain-desain museumnya-termasuk Museum of Modern Art (MoMA) New York-bahkan dengan bangga menyebut Hiroshima Naka Waste Incineration Plant sebagai desain “museum of garbage“nya. Pendekatan yang sama, namun dengan eksekusi yang berbeda terlihat di Osaka City Environmental Management Bureau’s Maishima Incineration and Water Treatment Plants, yang didesain oleh arsitek konservasi lingkungan terkenal dari Austria, Meister Friedensreich Hundertwasser. Fasilitas pengolahan sampah ini tampil bagai lukisan di atas kanvas sehingga lebih layak diduga sebagai theme park. Bentuk bangunan yang lebih dinamis, material yang sangat bervariasi, permainan bentuk dan warna pada elemen-elemen bangunan (jendela, pintu, langit-langit) serta penghijuan berhasil menyampaikan pesan positif “the harmony between ecology, technology, and art” yang ingin disampaikan oleh arsitek melalui fasilitas ini. Namun, kedua fasilitas ini menjadi lebih istimewa karena memang dibangun untuk memberikan “pelayanan” kepada masyarakat dan menjadi bagian dari masyarakat.
Fungsi publik dalam fasilitas pengolahan limbah
Usaha awal yang dilakukan pemerintah kota Hiroshima dan Osaka adalah dengan memasukkan fungsi incineration plant ini kedalam visi dan misi serta rencana infrastruktur pembangunan kawasan atau kota. Hiroshima Naka Incineration Plant tidak lain adalah bagian dari rencana kota Hiroshima untuk membangun infrastruktur-infrakruktur sosial kota sebagai bagian dari proyek “Hiroshima 2045: the city of Peace and Creation” sekaligus memperkuat tema “The Water City Hiroshima.“ Begitu juga Osaka Maishima Incineration Plant-yang berada tepat di pintu masuk pulau buatan ini-tidak lain adalah bagian penting dari masterplan kawasan Maishima sebagai “Maishima Sports Island” dan juga pendukung kota Osaka untuk memenangkan persaingan sebagai tuan rumah Olympiade Musim Panas 2008-yang direncanakan berpusat di pulau Maishima tersebut-saat itu.
Bangunan Hiroshima Naka Incineration Plant yang terdiri dari 1 lantai basement, 7 lantai kantor pengelola dan 1 lantai penthouse hanya menempati 27 persen dari luas total tapak sebesar 50,200m2, sementara sisanya didedikasikan bagi masyarakat dan kota Hiroshima dalam wujud waterfront park. Bangunan tersebut dibagi menjadi tiga zona oleh Taniguchi, dimana salah satu zona yang berada di bagian tengah disulap sebagai zona publik. Zona publik yang terdiri dari atrium dan dikelilingi oleh koridor viewing gallery ini memungkinkan masyarakat dapat melihat isi dari “perut” incinerator ini, serta pemandangan laut, pelabuhan dan kota Hiroshima. Kemudian, Taniguchi menempatkan walkway ecorium sepanjang 400 kaki menembus atrium tersebut. Ecorium ini memiliki fungsi istimewa sebagai media informasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui urutan proses dan teknologi pengolahan yang dimiliki; menghubungkan pemukiman dengan waterfront park baru yang berada di sisi selatan bangunan; dan juga memainkan peran simbolik sebagai gerbang yang menghubungkan laut dengan kota Hiroshima. Terakhir, fungsi ekologis fasilitas bagi kota dan kawasan sekitarnya ini dipertegas dengan ditanaminya pepohonan disekeliling bangunan dan juga di dalam atrium.
Begitu pula bangunan 7 lantai Osaka Maishima Incineration Plant membuka dirinya untuk masyarakat yang ingin mengetahui fasilitas pengolahan sampah ini sekaligus belajar mengenai manajeman pengolahan sampah kota Osaka. Masyarakat hanya perlu mendaftarkan diri satu minggu sebelumnya untuk mengikuti tour tersebut. Bangunan juga dibagi ke dalam 3 zona, dan Hundertwasser meletakkan lobby dan visitor observation deck di bagian tengah bangunan untuk memberi kesempatan bagi pengunjung melihat sebagian proses pengolah sampah berteknologi tinggi tersebut dan membuktikan bahwa sebuah TPS bisa menjadi tempat yang sangat bersih, indah dan berkesan modern. Dari luar, mosaic keramik, dan bentuk organis serta warna-warni semua elemen bangunan menjadi strategi tersendiri untuk mempercantik kawasan ini. Proses pendataan setiap truk-truk sampah yang masuk dan keluar fasilitas ini juga bisa disaksikan masyarakat dari luar bangunan. Fasilitas ini tidak luput dari unsur penghijauan yang berada di taman-taman yang mengelilinginya, di atap bangunan serta pohon-pohon yang menjulur keluar dari jendela-jendela bangunan.
Apa yang dilakukan oleh kedua fasilitas ini adalah mendekatkan diri kepada masyarakat dan membawa masyarakat menjadi satu bagian dari fasilitas dan permasalahan sampah kota, sehingga dengan menginformasikan proses pengolahan sampah, produksi sampah setiap hari nya, diharapkan mampu membuat masyarakat lebih sadar dalam mengelolah sampah nya.
Wisata Dan Studi Lingkungan Hidup Warga RT 6 RW 8 Kelurahan Sawunggaling Berlangsung Meriah
 Sekitar 100 orang warga kampung RT 6 RW 8 Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo bersama Tunas Hijau – kids & young people do actions for a better earth melakukan wisata dan studi banding lingkungan hidup. Kegiatan dalam rangkaian program pendampingan lingkungan hidup masyarakat stren Kali Surabaya bersama Badan Lingkungan Hidup Jawa Timur ini dilaksanakan Minggu (14/2). Obyek kunjungannya pun adalah tempat-tempat yang bernuansa lingkungan hidup. Yaitu Tempat Pembuangan Akhir sampah (TPA) Benowo, Kampung Jawara Surabaya Berbunga 2009 Gundih, Taman Flora Bratang, Rumah Kompos Bratang dan Jembatan Suramadu.
Sekitar 100 orang warga kampung RT 6 RW 8 Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo bersama Tunas Hijau – kids & young people do actions for a better earth melakukan wisata dan studi banding lingkungan hidup. Kegiatan dalam rangkaian program pendampingan lingkungan hidup masyarakat stren Kali Surabaya bersama Badan Lingkungan Hidup Jawa Timur ini dilaksanakan Minggu (14/2). Obyek kunjungannya pun adalah tempat-tempat yang bernuansa lingkungan hidup. Yaitu Tempat Pembuangan Akhir sampah (TPA) Benowo, Kampung Jawara Surabaya Berbunga 2009 Gundih, Taman Flora Bratang, Rumah Kompos Bratang dan Jembatan Suramadu. Seratus orang yang mengikuti kegiatan ini terdiri dari semua golongan usia. Ada anak-anak yang aktif dalam kegiatan kelompok belajar anak kampung ini, ada remaja karang taruna, ada bapak dan ibu pengurus kampung dan PKK, serta orang tua anak-anak. “Pada awalnya, kegiatan ini dikhususkan bagi anak-anak yang aktif di kelompok belajar anak dengan para pengajarnya. Namun karena antusiasme warga sangat besar untuk ikut serta, maka kami pun mengikutsertakan juga banyak ibu-ibu dan bapak-bapak,” kata aktivis senior Tunas Hijau Bram Azzaino yang mendampingi warga pada wisata lingkungan hidup ini.
Seratus orang yang mengikuti kegiatan ini terdiri dari semua golongan usia. Ada anak-anak yang aktif dalam kegiatan kelompok belajar anak kampung ini, ada remaja karang taruna, ada bapak dan ibu pengurus kampung dan PKK, serta orang tua anak-anak. “Pada awalnya, kegiatan ini dikhususkan bagi anak-anak yang aktif di kelompok belajar anak dengan para pengajarnya. Namun karena antusiasme warga sangat besar untuk ikut serta, maka kami pun mengikutsertakan juga banyak ibu-ibu dan bapak-bapak,” kata aktivis senior Tunas Hijau Bram Azzaino yang mendampingi warga pada wisata lingkungan hidup ini. Besarnya antusiasme warga itu ditunjukkan dengan kerelaan mereka untuk duduk berpangkuan mengoptimalkan 2 mini bus yang disediakan khusus oleh pemerintah kota Surabaya – Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. “Sedianya 2 mini bus yang digunakan ini hanya berkapasitas maksimal 40 kursi. Namun, orang tua yang berminat ikut tetap diperkenankan dengan memangku anaknya. Tambahan beberapa kursi panjang pun sengaja ditempatkan di kedua mini bus itu oleh warga,” tambah Bram Azzaino.
 Di tempat kunjungan pertama, TPA Benowo, warga dibuat kaget dengan pemandangan gunungan sampah dengan tinggi rata-rata 8 meter di lahan seluas 37 hektar atau 370.000 meter persegi. Memasuki gerbang TPA itu, rombongan yang ikut pun mulai sibuk menutup hidung mereka untuk menghalangi bau busuk. Di TPA ini rombongan dipandu oleh salah seorang pengelola TPA, Karjono, yang staf Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya. Bertempat di dekat instalasi pengolahan air lindi dan jembatan timbang, rombongan mendapat penjelasan tentang TPA Benowo itu.
Di tempat kunjungan pertama, TPA Benowo, warga dibuat kaget dengan pemandangan gunungan sampah dengan tinggi rata-rata 8 meter di lahan seluas 37 hektar atau 370.000 meter persegi. Memasuki gerbang TPA itu, rombongan yang ikut pun mulai sibuk menutup hidung mereka untuk menghalangi bau busuk. Di TPA ini rombongan dipandu oleh salah seorang pengelola TPA, Karjono, yang staf Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya. Bertempat di dekat instalasi pengolahan air lindi dan jembatan timbang, rombongan mendapat penjelasan tentang TPA Benowo itu. Disampaikan Karjono bahwa TPA itu beroperasi sejak tahun 2001. “Peran serta aktif warga Kota Surabaya sangat diharapkan untuk memperpanjang waktu beroperasinya TPA Benowo ini,” kata Karjono. Caranya, dengan sedapatnya mengolah sampah yang dihasilkan. “Dengan demikian jumlah sampah yang dikirim setiap harinya ke TPA ini berkurang. Bila setiap hari 1200 ton sampah warga Kota Surabaya dikirim ke TPA ini seperti saat ini, maka umur TPA ini tidak akan lebih dari lima tahun. Setelah itu, kita diharuskan mencari lahan baru untuk TPA sampah,” terang Karjono.
 Mendengar penjelasan Karjono itu, aktivis senior Tunas Hijau Mochamad Zamroni ikut urun bicara. Disampaikan Zamroni bahwa sejak beberapa minggu lalu ada tambahan komposter aerob, keranjang komposter takakura dan gerobak sampah yang diberikan kepada warga RT 6 RW 8 Kelurahan Sawunggaling. “Perangkat-perangkat pengolahan sampah itu diberikan dengan tujuan warga kampung mau mengolah sampah dan mengurangi jumlah sampah yang dikirimkan ke TPA Benowo. Makanya, mari kita optimalkan pengolahan sampah di kampung kita,” kata Zamroni.
Mendengar penjelasan Karjono itu, aktivis senior Tunas Hijau Mochamad Zamroni ikut urun bicara. Disampaikan Zamroni bahwa sejak beberapa minggu lalu ada tambahan komposter aerob, keranjang komposter takakura dan gerobak sampah yang diberikan kepada warga RT 6 RW 8 Kelurahan Sawunggaling. “Perangkat-perangkat pengolahan sampah itu diberikan dengan tujuan warga kampung mau mengolah sampah dan mengurangi jumlah sampah yang dikirimkan ke TPA Benowo. Makanya, mari kita optimalkan pengolahan sampah di kampung kita,” kata Zamroni. Setelah mendapat banyak penjelasan tentang TPA Benowo, rombongan lantas diajak meneruskan perjalanan ke zona aktif TPA Benowo, yaitu kawasan dimana sampah dari seluruh warga kota ditempatkan. Di zona aktif itu rombongan menyaksikan pemandangan banyaknya gubuk non permanen yang sengaja dibuat para pemulung untuk melakukan pengumpulan sampah non organik. Ratusan hingga ribuan pemulung yang asyik berburu sampah non organik khususnya plastik menjadi pemandangan unik bagi rombongan.
Setelah mendapat banyak penjelasan tentang TPA Benowo, rombongan lantas diajak meneruskan perjalanan ke zona aktif TPA Benowo, yaitu kawasan dimana sampah dari seluruh warga kota ditempatkan. Di zona aktif itu rombongan menyaksikan pemandangan banyaknya gubuk non permanen yang sengaja dibuat para pemulung untuk melakukan pengumpulan sampah non organik. Ratusan hingga ribuan pemulung yang asyik berburu sampah non organik khususnya plastik menjadi pemandangan unik bagi rombongan. Kurang dari lima menit berada di terminal zona aktif itu, dari sekitar 30 menit waktu yang disediakan, rombongan lantas mengusulkan untuk meneruskan perjalanan ke lokasi kunjungan selanjutnya. “Anak-anak dan ibu-ibu banyak yang muntah dan mau pingsan, Mas. Mereka gak kuat dengan sangat menyengatnya bau sampah di lokasi ini,” kata Slamet Hariadi, koordinator kelompok swadaya masyarakat RT 6 RW 8 Kelurahan Sawunggaling di yang menyertai rombongan.
 Setelah selesai melakukan kunjungan di TPA Benowo, rombongan lantas melanjutkan perjalanan ke kampung Gundih yang menjadi Jawara Surabaya Berbunga 2009. Di kampung ini rombongan juga dibuat kagum dengan begitu bersih dan hijaunya kampung yang sebenarnya berada di lokasi kumuh. Lebar jalan di kampung itu juga tidak cukup untuk dua becak masuk bersamaan. Tidak ada sampah yang dibuang sembarangan di kampung itu. Pun tidak ada satu jengkal lahan yang tanpa tanaman, meskipun dalam pot-potan.
Setelah selesai melakukan kunjungan di TPA Benowo, rombongan lantas melanjutkan perjalanan ke kampung Gundih yang menjadi Jawara Surabaya Berbunga 2009. Di kampung ini rombongan juga dibuat kagum dengan begitu bersih dan hijaunya kampung yang sebenarnya berada di lokasi kumuh. Lebar jalan di kampung itu juga tidak cukup untuk dua becak masuk bersamaan. Tidak ada sampah yang dibuang sembarangan di kampung itu. Pun tidak ada satu jengkal lahan yang tanpa tanaman, meskipun dalam pot-potan. Rombongan lantas dipandu salah seorang kader lingkungan hidup kampung Gundih, Wiwik, yang menjadi instruktur pelatihan daur ulang sampah plastik kampung stren Kali Surabaya Gunungsari II pertengahan Desember 2009. “Selamat datang di kampung saya. Akhirnya ibu-ibu berkunjung ke kampung saya setelah dua kali kami mengunjungi kampung ibu-ibu untuk pelatihan daur ulang sampah plastik,” kata Wiwik yang mengenakan kaos kader lingkungan saat menyambut rombongan.
Rombongan lantas dipandu salah seorang kader lingkungan hidup kampung Gundih, Wiwik, yang menjadi instruktur pelatihan daur ulang sampah plastik kampung stren Kali Surabaya Gunungsari II pertengahan Desember 2009. “Selamat datang di kampung saya. Akhirnya ibu-ibu berkunjung ke kampung saya setelah dua kali kami mengunjungi kampung ibu-ibu untuk pelatihan daur ulang sampah plastik,” kata Wiwik yang mengenakan kaos kader lingkungan saat menyambut rombongan. Beberapa menit setelah menginjakkan kaki di kampung Gundih, beberapa komentar positif pun dilontarkan oleh ibu-ibu dari Kelurahan Sawunggaling ini. “Bu RT, coba lihat tanaman-tanaman dalam pot yang sangat banyak dipelihara di kampung ini. Sebenarnya tanaman-tanaman itu bukan tanaman yang harganya mahal. Namun, jumlahnya banyak dan pengaturannya sangat bagus sehingga kesannya sangat eksklusif,” kata salah satu ibu kepada Siti Aminah yang istri ketua RT 6 RW 8 Kelurahan Sawunggaling. “Ayo, Bu RT, kita buat kampung kita seperti ini,” lanjut ibu itu.
 Joko Sukaryono, koordinator pemberdayaan ekonomi Kelompok Swadaya Masyarakat RT 6 RW 8 Kelurahan Sawunggaling mengatakan bahwa wisata dan studi banding lingkungan hidup yang dilakukan ini benar-benar sangat berkesan. “Kegiatan ini berbeda dengan wisata umumnya. Kegiatan ini sangat ekonomis namun dampaknya bagi kami sangat besar. Saya pribadi dan beberapa orang lain warga kampung yang mengikuti kegiatan ini seperti mendapat suntikan semangat untuk membenahi kampung menjadi bersih, hijau dan nyaman,” kata Joko Sukaryono sesaat setelah mengamati kondisi kampung Gundih Gang VI.
Joko Sukaryono, koordinator pemberdayaan ekonomi Kelompok Swadaya Masyarakat RT 6 RW 8 Kelurahan Sawunggaling mengatakan bahwa wisata dan studi banding lingkungan hidup yang dilakukan ini benar-benar sangat berkesan. “Kegiatan ini berbeda dengan wisata umumnya. Kegiatan ini sangat ekonomis namun dampaknya bagi kami sangat besar. Saya pribadi dan beberapa orang lain warga kampung yang mengikuti kegiatan ini seperti mendapat suntikan semangat untuk membenahi kampung menjadi bersih, hijau dan nyaman,” kata Joko Sukaryono sesaat setelah mengamati kondisi kampung Gundih Gang VI. Kekaguman juga diungkapkan oleh penggiat daur ulang kampung Sawunggaling/Gunungsari, Siti Fatimah saat melihat aneka macam produk daur ulang sampah plastik yang dipajang dan dijual di salah satu sudut kampung. “Bentuk produk daur ulangnya sangat banyak dan bervariasi. Penuh inovasi. Saya jadi termotivasi untuk terus mengembangkan daur ulang bersama warga kampung sepulang dari kunjungan ini. Saya banyak mendapat tambahan ide dari kunjungan ini,” kata Siti Fatimah sesaat setelah mengamati produk-produk daur ulang sampah plastik yang dipajang.
Kekaguman juga diungkapkan oleh penggiat daur ulang kampung Sawunggaling/Gunungsari, Siti Fatimah saat melihat aneka macam produk daur ulang sampah plastik yang dipajang dan dijual di salah satu sudut kampung. “Bentuk produk daur ulangnya sangat banyak dan bervariasi. Penuh inovasi. Saya jadi termotivasi untuk terus mengembangkan daur ulang bersama warga kampung sepulang dari kunjungan ini. Saya banyak mendapat tambahan ide dari kunjungan ini,” kata Siti Fatimah sesaat setelah mengamati produk-produk daur ulang sampah plastik yang dipajang.
Di kampung Gundih itu rombongan tidak hanya disuguhi dengan keadaan kampung yang bersih dan hijau dengan tingginya partisipasi aktif seluruh warga kampung itu. Rombongan juga banyak mendapat penjelasan tentang instalasi pengolahan air limbah rumah tangga yang dibuat oleh warga kampung. “Instalasi pengolahan ini sangat sederhana. Cara kerjanya sangat alami. Namun, dampaknya sangat besar. Kami tidak khawatir tagihan air PDAM menjadi mahal karena tingginya perawatan seluruh tanaman di kampung ini. Kami mengolah air limbah dari seluruh rumah warga untuk bisa layak digunakan menyiram tanaman,” kata salah seorang pengurus pengolahan air limbah di kampung itu.
 Setelah kunjungan di kampung Gundih – Jawara Surabaya Berbunga 2009, rombongan melanjutkan perjalanan ke Taman Flora Bratang dan Rumah Kompos Bratang. Di Taman Flora Bratang, rombongan beristirahat sambil makan siang dan sholat dhuhur. Di taman ini rombongan juga mereview hasil kunjungan di dua tempat sebelumnya, yaitu TPA Benowo dan kampung Gundih. Sementara rombongan orang tua melakukan review, anak-anak memanfaatkannya untuk bermain-main menggunakan beberapa permainan yang disediakan di taman itu.
Setelah kunjungan di kampung Gundih – Jawara Surabaya Berbunga 2009, rombongan melanjutkan perjalanan ke Taman Flora Bratang dan Rumah Kompos Bratang. Di Taman Flora Bratang, rombongan beristirahat sambil makan siang dan sholat dhuhur. Di taman ini rombongan juga mereview hasil kunjungan di dua tempat sebelumnya, yaitu TPA Benowo dan kampung Gundih. Sementara rombongan orang tua melakukan review, anak-anak memanfaatkannya untuk bermain-main menggunakan beberapa permainan yang disediakan di taman itu. Selesai beraktivitas di Taman Flora Bratang, rombongan lantas melanjutkan aktivitas di Rumah Kompos Bratang, yang letaknya di selatan Taman Flora Bratang. Di rumah kompos ini rombongan belajar tentang cara pengolahan sampah organik dalam jumlah besar. Sementara para orang tua terlibat diskusi dengan petugas rumah kompos itu, anak-anak diberi kesempatan melakukan pengomposan. Mulai perajangan, pembalikan dan pengayakan kompos dilakukan oleh anak-anak. Kunjungan ke Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dan Madura menjadi kegiatan penutup wisata dan studi banding lingkungan hidup yang digelar pagi hingga sore itu.
Selesai beraktivitas di Taman Flora Bratang, rombongan lantas melanjutkan aktivitas di Rumah Kompos Bratang, yang letaknya di selatan Taman Flora Bratang. Di rumah kompos ini rombongan belajar tentang cara pengolahan sampah organik dalam jumlah besar. Sementara para orang tua terlibat diskusi dengan petugas rumah kompos itu, anak-anak diberi kesempatan melakukan pengomposan. Mulai perajangan, pembalikan dan pengayakan kompos dilakukan oleh anak-anak. Kunjungan ke Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dan Madura menjadi kegiatan penutup wisata dan studi banding lingkungan hidup yang digelar pagi hingga sore itu. Jumat, 17 September 2010
2011 Jabar Bebas Lahan Kritis
BANDUNG-–Memasuki tahun 2010 seluruh lahan kritis di Jabar akan dihijaukan melalui program Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK) dengan dana sekitar Rp 30 miliar per tahun. Dengan demikian pada tahun 2011 Jabar akan dinobatkan sebagai provinsi bebas lahan kritis.
Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Jabar, menunjukkan, tahun 2003 luas lahan kritis di Jabar seluas 580.394 hektare. Hingga akhir tahun 2008, sisa lahan kritis di Jabar tinggal 176 ribu hektare. Sepanjang lima tahun ini, sedikitnya 404.394 hektare lahan kritis telah dihijaukan. Sisa lahan kritis tersebut, akan dituntaskan hingga tahun 2010.
Gubenrur Jabar, Ahmad Heryawan, menjelaskan, lahan kritis di Jabar akan ditanggulangi melalui program Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK). Dia mengaku, program tersebut berlangsung mulai dari 2003 hingga 2010. Setiap tahunnya, jelas dia, lahan alokasi dana untuk program GRLK berkisar Rp 25-30 miliar.
Heryawan menjelaskan, GRLK merupakan kegiatan pembangunan lingkungan yang melibatkan masyarakat. Dia menyatakan, melalui program tersebut, petani hutan akan diperankan dalam melindungi hutan.
Bibit pohon keras yang akan ditanam melalui program itu, jelas dia, berasal dari penangkar tradisional. Menurut Heryawan, bibit pohon keras itu, jelas dia, akan disalurkan melalui elompok tani yang selama ini berdomisili di kawasan hutan.
Dipaparkan Heryawan, saat ini terdapat kelompok masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan penghijauan lahan kritis. Di antaranya, Asosiasi Kepala Desa Sekitar Hutan Negara (AKSHN), Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (GAPPERINDO), Kontak Tani Hutan Andalan (KTHA), dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).
Kata dia, jenis pohon yang didistribusikan melalui program tersebut berupa pohon hutan dan pohon buah-buahan. Intinya, jelas dia, pohon yang ditanam melalui program tersebut harus memiliki fungsi konservasi.
Hasil dari pohon buah-buahan itu, lanjut Heryawan, akan menjadi keuntungan warga yang dipercaya mengelola pohon tersebut. ‘’Kondisi lingkungan yang memadai, tentu akan menunjang kegiatan pertanian lainnya. Paling tidak, ketersediaan airnya aman,’’ ujar Heryawan saat makan siang dengan wartawan di kantin Gedung Sate, Bandung, Jumat (20/11).
Kepala Dinas Kehutanan Jabar, Anang Sudarna, menyebutkan, program GRLK pun akan menyentuh pula sekitar 7.500 hektare lahan di empat daerah aliran sungai (DAS) di Jabar. Empat DAS itu, papar dia, yakni Citarum, Citanduy, Cimanuk, dan Cisanggarung.
Kata Anang, tidak hanya melalui GRLK, tahun ini pun hutan kritis di Jabar akan dihijaukan melalui Departemen Kehutanan seluas 46 ribu hektare. Sementara total lahan kritis di Jabar, papar dia, mencapai 170 ribu hektare.
Menurut Anang, antara program GRLK dan Dephut dipastikan tidak akan tumpang tindih. Dia menjelaskan, GRLK dipastikan tidak akan direalisasikan pada lahan yang sudah ditanggulangi Dephut.
Ditambahkan Anang, selain di kawasan hutan, budaya menanam pohon harus digalakan di lokasi pemukiman. Dia menjelaskan, selama ini pembangunan infrastruktur di daerah perkotaan kerap melupakan bahkan mengikis ruang terbuka hijau (RTH). ‘’Sedikitnya setiap kepala keluarga harus menanam satu pohon,'' ujar Anang di kantornya, Jumat (20/11). Pengusaha dan pelajar pun, tambah dia, sebisa mungkin menggalakan budaya menanam pohon.
Ketua Forum Penyelamat Lingkungan Hidup (FPLH), Thio Setiowekti, menjelaskan, program GRLK tidak cukup pada tahapan penanaman. Dia menyatakan, banyak pohon yang ditanam melalui GRLK mati akibat tidak dirawat. ‘’Kami mohon Dishut juga memperhatikan dan memelihara pohon yang sudah ditanamnya,’’ ujar Thio kepada Republika, Jumat (20/11). Dia mengaku, saat ini tidak sedikit pohon yang ditanam melalui GRLK yang sengaja dicabut oleh mafia hutan.
Dia menyatakan, pohon tersebut sengaja dicabut agar lahannya bisa ditanami sayuran. Thio mengakui, keuntungan dari komoditas sayuran lebih cepat ketimbang pohon buah-buahan. Namun, jelas dia, tanaman sayuran tidak memiliki fungsi konservasi.
Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Jabar, menunjukkan, tahun 2003 luas lahan kritis di Jabar seluas 580.394 hektare. Hingga akhir tahun 2008, sisa lahan kritis di Jabar tinggal 176 ribu hektare. Sepanjang lima tahun ini, sedikitnya 404.394 hektare lahan kritis telah dihijaukan. Sisa lahan kritis tersebut, akan dituntaskan hingga tahun 2010.
Gubenrur Jabar, Ahmad Heryawan, menjelaskan, lahan kritis di Jabar akan ditanggulangi melalui program Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK). Dia mengaku, program tersebut berlangsung mulai dari 2003 hingga 2010. Setiap tahunnya, jelas dia, lahan alokasi dana untuk program GRLK berkisar Rp 25-30 miliar.
Heryawan menjelaskan, GRLK merupakan kegiatan pembangunan lingkungan yang melibatkan masyarakat. Dia menyatakan, melalui program tersebut, petani hutan akan diperankan dalam melindungi hutan.
Bibit pohon keras yang akan ditanam melalui program itu, jelas dia, berasal dari penangkar tradisional. Menurut Heryawan, bibit pohon keras itu, jelas dia, akan disalurkan melalui elompok tani yang selama ini berdomisili di kawasan hutan.
Dipaparkan Heryawan, saat ini terdapat kelompok masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan penghijauan lahan kritis. Di antaranya, Asosiasi Kepala Desa Sekitar Hutan Negara (AKSHN), Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (GAPPERINDO), Kontak Tani Hutan Andalan (KTHA), dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).
Kata dia, jenis pohon yang didistribusikan melalui program tersebut berupa pohon hutan dan pohon buah-buahan. Intinya, jelas dia, pohon yang ditanam melalui program tersebut harus memiliki fungsi konservasi.
Hasil dari pohon buah-buahan itu, lanjut Heryawan, akan menjadi keuntungan warga yang dipercaya mengelola pohon tersebut. ‘’Kondisi lingkungan yang memadai, tentu akan menunjang kegiatan pertanian lainnya. Paling tidak, ketersediaan airnya aman,’’ ujar Heryawan saat makan siang dengan wartawan di kantin Gedung Sate, Bandung, Jumat (20/11).
Kepala Dinas Kehutanan Jabar, Anang Sudarna, menyebutkan, program GRLK pun akan menyentuh pula sekitar 7.500 hektare lahan di empat daerah aliran sungai (DAS) di Jabar. Empat DAS itu, papar dia, yakni Citarum, Citanduy, Cimanuk, dan Cisanggarung.
Kata Anang, tidak hanya melalui GRLK, tahun ini pun hutan kritis di Jabar akan dihijaukan melalui Departemen Kehutanan seluas 46 ribu hektare. Sementara total lahan kritis di Jabar, papar dia, mencapai 170 ribu hektare.
Menurut Anang, antara program GRLK dan Dephut dipastikan tidak akan tumpang tindih. Dia menjelaskan, GRLK dipastikan tidak akan direalisasikan pada lahan yang sudah ditanggulangi Dephut.
Ditambahkan Anang, selain di kawasan hutan, budaya menanam pohon harus digalakan di lokasi pemukiman. Dia menjelaskan, selama ini pembangunan infrastruktur di daerah perkotaan kerap melupakan bahkan mengikis ruang terbuka hijau (RTH). ‘’Sedikitnya setiap kepala keluarga harus menanam satu pohon,'' ujar Anang di kantornya, Jumat (20/11). Pengusaha dan pelajar pun, tambah dia, sebisa mungkin menggalakan budaya menanam pohon.
Ketua Forum Penyelamat Lingkungan Hidup (FPLH), Thio Setiowekti, menjelaskan, program GRLK tidak cukup pada tahapan penanaman. Dia menyatakan, banyak pohon yang ditanam melalui GRLK mati akibat tidak dirawat. ‘’Kami mohon Dishut juga memperhatikan dan memelihara pohon yang sudah ditanamnya,’’ ujar Thio kepada Republika, Jumat (20/11). Dia mengaku, saat ini tidak sedikit pohon yang ditanam melalui GRLK yang sengaja dicabut oleh mafia hutan.
Dia menyatakan, pohon tersebut sengaja dicabut agar lahannya bisa ditanami sayuran. Thio mengakui, keuntungan dari komoditas sayuran lebih cepat ketimbang pohon buah-buahan. Namun, jelas dia, tanaman sayuran tidak memiliki fungsi konservasi.
FOSIL GAJAH BERUSIA 250 JUTA TAHUN
Bojonegoro (berita2.com): Fosil yang ditemukan seorang guru SDN, Hary Nugroho (45), di Waduk Daya`an di Desa Wotangare, Kecamatan Kalitidu, Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis (12/11), diperkirakan fosil gajah purba atau "setegodon". dengan usia 250 juta tahun.
Camat Kalitidu, Nurul Azizah, Rabu menjelaskan, perkiraan fosil yang ditemukan di galian waduk, berupa kepala, gading, tulang kaki dan taring tersebut, merupakan fosil gajah purba. Kesimpulan ini, berdasarkan penelitian sementara tim dari Balai Penelitian Peninggalan Purbakala (BP3) Trowulan, Mojokerto.
Dari hasil kajian tim yang melakukan penelitian temuan itu dan langsung di lapangan, memperkirakan usia fosil tersebut, berkisar 250 juta tahun yang lalu. "Hanya fosil gajah purba tersebut dari jenis apa, masih dibutuhkan penelitian lanjutan," katanya.
Sementara ini, temuan fosil gajah purba yang semula disimpan di SDN Panjunan I dan II, Desa Panjunan, Kecamatan Kalitidu, sekarang ini, disimpan di kediaman Kepala Desa Wotangare, Kecamatan Kalitidu. Tim BP 3 Trowulan, yang datang ke Bojonegoro, juga melakukan penelitian temuan emas di perairan Bengawan Solo di Desa Ngraho, Kecamatan Kalitidu.
Menurut ia, dari hasil penelitian tim, adanya temuan emas di perairan Bengawan Solo tersebut, berasal dari muatan sebuah kapal yang tenggelam di perairan setempat."Hanya kepastiannya masih membutuhkan penelitian lebih mendalam," katanya menjelaskan.
Hary Nugroho (45), guru SDN Panjunan I dan II di Desa Panjunan, Kecamatan Kalitidu, sejak 1990 lalu, memiliki kebiasaan mengumpulkan fosil yang ada di wilayah Bojonegoro dan terakhir menemukan fosil gajah purba di galian Waduk Daya`an.
Di antara temuan Harry Nugroho yang sekarang disimpan di SDN Panjunan I dan II yaitu ratusan fragmen fosil dari karabau (kerbau purba), cervia (kijang), stegodon trigono chepalus, mastodon, elephas, babos dan bubalus
Planting 1 Billion Trees in 2010
Perum Perhutani cooperates with a number of SOEs and private sectors to realize a Billion Tree planting ini.Saat years alone, said president director of Perum Perhutani, Rosalina Upiek Wasrin, in Jakarta on Tuesday, his side has received commitments from five state-owned companies will contribute to fund the planting of 200 million trees valued at Rp20 billion.
That commitment is part of planting a billion trees that are targeted by the government in order to land and forest rehabilitation are critical, according to him after receiving Tadina Band as part of the Forest Village Community Institution (LMDH) Plus Perum Perhutani. "As part of the synergy between state-owned, we currently can get a commitment from the five SOEs. Synergies that will be our effort to expand, through encouraging other SOEs and private, such as the Lippo Group and Sentul," said Upiek.
To a successful five state-owned Perhutani drawn to those involved in planting, PT Pertamina (Persero), Semen Gresik, Pupuk Kujang, PT Antam Tbk., And PT Kereta Api. They will be involved in the preparation of the seeds to be planted until November will reach 200 million trees. "Production of seedlings for planting this could even reach 500 million trees, if coupled with private commitments like Lippo or Sentul area managers, and Cikampek Nusantara Bonded Zone are we going to hook up," said Upiek.
Meanwhile, the Ministry of Forestry also continue to urge and invite "stakeholders" to succeed Planting a Billion Trees. Earlier, Director General of Land and Social Forestry Rehabiitasi (RLPS, Ministry of Forestry, Indriastuti, admits the realization of the plants continued program One Man One Three has already reached 34 million trees.
According to him, the realization of that investment is a combination of rehabilitation programs and cooperation of the Ministry is woven with those of community organizations and private parties. "I initiated the planting along with a number of organizations, such as NU Fatayat, universities, Aero Seedling Indonesia, Al Ghiffari FOrest Community Indonesia and other parties," he said.
Ministry of Forestry, said Indri, also prepared 800 People Nursery (KBR) with an allocation of funds this year to Rp400 billion. "KBR is we submit to the district or village, located on public lands. For a Billion Tree planting, the community can also benefit from the results of non-wood," said Indri.
That commitment is part of planting a billion trees that are targeted by the government in order to land and forest rehabilitation are critical, according to him after receiving Tadina Band as part of the Forest Village Community Institution (LMDH) Plus Perum Perhutani. "As part of the synergy between state-owned, we currently can get a commitment from the five SOEs. Synergies that will be our effort to expand, through encouraging other SOEs and private, such as the Lippo Group and Sentul," said Upiek.
To a successful five state-owned Perhutani drawn to those involved in planting, PT Pertamina (Persero), Semen Gresik, Pupuk Kujang, PT Antam Tbk., And PT Kereta Api. They will be involved in the preparation of the seeds to be planted until November will reach 200 million trees. "Production of seedlings for planting this could even reach 500 million trees, if coupled with private commitments like Lippo or Sentul area managers, and Cikampek Nusantara Bonded Zone are we going to hook up," said Upiek.
Meanwhile, the Ministry of Forestry also continue to urge and invite "stakeholders" to succeed Planting a Billion Trees. Earlier, Director General of Land and Social Forestry Rehabiitasi (RLPS, Ministry of Forestry, Indriastuti, admits the realization of the plants continued program One Man One Three has already reached 34 million trees.
According to him, the realization of that investment is a combination of rehabilitation programs and cooperation of the Ministry is woven with those of community organizations and private parties. "I initiated the planting along with a number of organizations, such as NU Fatayat, universities, Aero Seedling Indonesia, Al Ghiffari FOrest Community Indonesia and other parties," he said.
Ministry of Forestry, said Indri, also prepared 800 People Nursery (KBR) with an allocation of funds this year to Rp400 billion. "KBR is we submit to the district or village, located on public lands. For a Billion Tree planting, the community can also benefit from the results of non-wood," said Indri.
Rabu, 15 September 2010
Sampah di Kepulauan Seribu Ancam Taman Laut
[JAKARTA] Pembuangan sampah di perairan Kepulauan Seribu semakin memprihatinkan. Sampah yang berasal dari 13 anak sungai di Jakarta itu, kini mengancam kawasan taman nasional laut.
Menurut Bupati Kepulauan Seribu, Djoko Ramadhan, penumpukan sampah di perairan Kepulauan Seribu pada 2005, sudah sejauh 45 kilometer dari pinggir pantai utara Jakarta.
"Tahun ini, sampah yang masuk ke perairan Kepulauan Seribu bisa mencapai 65 kilometer. Soalnya, volume sampah dari 13 aliran sungai di Jakarta, sekitar 300 meter kubik per hari," kata Djoko, di Jakarta, Rabu (10/5).
Dia mengatakan, penumpukan sampah yang sejauh 65 kilometer itu, semakin mendekati kawasan taman nasional laut. Saat ini, sampah dari daratan Jakarta sudah memasuki zona penyangga taman nasional laut, antara lain di Pulau Pramuka, Pulau Panggang, Pulau Kelapa, dan Pulau Harapan.
"Kalau masalah ini, tidak diperhatikan secara serius, dalam beberapa tahun ke depan bisa mencapai zona inti taman nasional laut yang merupakan kawasan konservasi dan cagar alam," ujar Djoko.
Dia mengungkapkan, sudah banyak pengelola resort yang mengeluhkan keberadaan sampah di sekitar perairan Kepulauan Seribu. Kondisi itu, dirasakan mengganggu kegiatan pariwisata di Kepulauan Seribu yang memang mengandalkan potensi laut.
Jika masalah sampah tidak segera diatasi, lanjut Djoko, bukan tidak mungkin angka kunjungan wisatawan ke Kepulauan Seribu akan berkurang. "Makanya, perlu ada gerakan pembersihan sampah secara menyeluruh baik di laut maupun di daratan terutama di 13 sungai di daratan Jakarta," kata Djoko.
Saat ini, lanjutnya, Kepulauan Seribu hanya mampu menyetor ke kas daerah sebesar Rp 2 miliar per tahun dari sektor pariwisata. Setoran itu, berasal dari kunjungan wisatwan ke sembilan pulau yang dikhususkan untuk kegiatan pariwisata, antara lain Pulau Ayer, Matahari, Bidadari, Putri, dan Kotok Timur.
Padahal ada 45 pulau yang dikhususkan untuk resort atau kunjungan wisatawan. "Kalau 45 pulau bisa aktif, setoran ke kas daerah bisa mencapai Rp 90 miliar," ujar Djoko.
Tidak Terangkut
Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI, Mukhayar RM, mengatakan, sampah yang menumpuk di perairan Kepulauan Seribu kebanyakan berasal dari sampah warga yang dibuang ke sungai.
Hal itu, lanjutnya, disebabkan sekitar 20 persen dari 20 ton sampai 30 ton sampah per hari di setiap kelurahan tidak terangkut ke tempat pembuangan akhir. Akibatnya, warga membuang sampah di sungai.
"Contohnya di Kampung Melayu. Banyak papan bertuliskan jangan buang sampah di sini, buang aje ke kali," kata Mukhayar yang merupakan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Sementara itu, Komisaris PT Asiana Technologies Lestary, Poltak Sitinjak, mengatakan, sampah yang terbuang ke Kepulauan Seribu paling banyak dari Cengkareng Drain dan Banjir Kanal Barat (BKB). PT Asiana Technologies Lestary adalah operator alat penyaring sampah di Jakarta.
"Cengakareng Drain dan BKB lebarnya sekitar 80 meter, cukup lebar dibanding sungai yang lain, sehingga daya tampung terhadap sampah banyak sekali," kata Poltak.
Menurut dia, pembersihan sampah di sungai kini tidak mungkin lagi dilakukan dengan cara manual yang memanfaatkan tenaga manusia. Namun, perlu adanya teknologi canggih berupa penyaring sampah otomatis.
PT Asiana kini telah memasang sejumlah alat penyaring sampah otomatis mekanikal elektrikal hydraulic di Sungai Cideng, Waduk Pluit, Teluk Gong, dan Sungai Sunter. Alat penyaring itu, mampu mengangkat sampah sebanyak 135 meter kubik per hari.
Untuk tahun ini, pihaknya akan kembali memasang lima penyaring sampah otomatis di Pulomas, Rumah Pompa Waduk Selatan, Sungai Grogol, dan Mookevart. Nilai investasinya Rp 25 miliar dengan bermitra dengan Pemprov DKI Jakarta
Menurut Bupati Kepulauan Seribu, Djoko Ramadhan, penumpukan sampah di perairan Kepulauan Seribu pada 2005, sudah sejauh 45 kilometer dari pinggir pantai utara Jakarta.
"Tahun ini, sampah yang masuk ke perairan Kepulauan Seribu bisa mencapai 65 kilometer. Soalnya, volume sampah dari 13 aliran sungai di Jakarta, sekitar 300 meter kubik per hari," kata Djoko, di Jakarta, Rabu (10/5).
Dia mengatakan, penumpukan sampah yang sejauh 65 kilometer itu, semakin mendekati kawasan taman nasional laut. Saat ini, sampah dari daratan Jakarta sudah memasuki zona penyangga taman nasional laut, antara lain di Pulau Pramuka, Pulau Panggang, Pulau Kelapa, dan Pulau Harapan.
"Kalau masalah ini, tidak diperhatikan secara serius, dalam beberapa tahun ke depan bisa mencapai zona inti taman nasional laut yang merupakan kawasan konservasi dan cagar alam," ujar Djoko.
Dia mengungkapkan, sudah banyak pengelola resort yang mengeluhkan keberadaan sampah di sekitar perairan Kepulauan Seribu. Kondisi itu, dirasakan mengganggu kegiatan pariwisata di Kepulauan Seribu yang memang mengandalkan potensi laut.
Jika masalah sampah tidak segera diatasi, lanjut Djoko, bukan tidak mungkin angka kunjungan wisatawan ke Kepulauan Seribu akan berkurang. "Makanya, perlu ada gerakan pembersihan sampah secara menyeluruh baik di laut maupun di daratan terutama di 13 sungai di daratan Jakarta," kata Djoko.
Saat ini, lanjutnya, Kepulauan Seribu hanya mampu menyetor ke kas daerah sebesar Rp 2 miliar per tahun dari sektor pariwisata. Setoran itu, berasal dari kunjungan wisatwan ke sembilan pulau yang dikhususkan untuk kegiatan pariwisata, antara lain Pulau Ayer, Matahari, Bidadari, Putri, dan Kotok Timur.
Padahal ada 45 pulau yang dikhususkan untuk resort atau kunjungan wisatawan. "Kalau 45 pulau bisa aktif, setoran ke kas daerah bisa mencapai Rp 90 miliar," ujar Djoko.
Tidak Terangkut
Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI, Mukhayar RM, mengatakan, sampah yang menumpuk di perairan Kepulauan Seribu kebanyakan berasal dari sampah warga yang dibuang ke sungai.
Hal itu, lanjutnya, disebabkan sekitar 20 persen dari 20 ton sampai 30 ton sampah per hari di setiap kelurahan tidak terangkut ke tempat pembuangan akhir. Akibatnya, warga membuang sampah di sungai.
"Contohnya di Kampung Melayu. Banyak papan bertuliskan jangan buang sampah di sini, buang aje ke kali," kata Mukhayar yang merupakan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Sementara itu, Komisaris PT Asiana Technologies Lestary, Poltak Sitinjak, mengatakan, sampah yang terbuang ke Kepulauan Seribu paling banyak dari Cengkareng Drain dan Banjir Kanal Barat (BKB). PT Asiana Technologies Lestary adalah operator alat penyaring sampah di Jakarta.
"Cengakareng Drain dan BKB lebarnya sekitar 80 meter, cukup lebar dibanding sungai yang lain, sehingga daya tampung terhadap sampah banyak sekali," kata Poltak.
Menurut dia, pembersihan sampah di sungai kini tidak mungkin lagi dilakukan dengan cara manual yang memanfaatkan tenaga manusia. Namun, perlu adanya teknologi canggih berupa penyaring sampah otomatis.
PT Asiana kini telah memasang sejumlah alat penyaring sampah otomatis mekanikal elektrikal hydraulic di Sungai Cideng, Waduk Pluit, Teluk Gong, dan Sungai Sunter. Alat penyaring itu, mampu mengangkat sampah sebanyak 135 meter kubik per hari.
Untuk tahun ini, pihaknya akan kembali memasang lima penyaring sampah otomatis di Pulomas, Rumah Pompa Waduk Selatan, Sungai Grogol, dan Mookevart. Nilai investasinya Rp 25 miliar dengan bermitra dengan Pemprov DKI Jakarta
HIMPALAUNAS, JAKARTA - Kondisi terumbu karang di Indonesia semakin memprihatinkan menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), M Syamsul Maarif , hanya sekitar 30 persen dari terumbu karang di perairan Indonesia dalam kondisi baik.
"Karang kita yang kondisinya baik sekitar 30 persen," kata Syamsul Maarif dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) KKP dan World Wildlife Fund (WWF) Indonesia di Kantor KKP, Jakarta, Senin (23/8) lalu.
Ia juga menuturkan, selain 30 persen karang yang berkondisi baik, jumlah karang yang kondisinya sangat baik adalah jauh lebih kecil lagi hanya sekitar enam persen.
Sedangkan sisanya, lanjut Sekjen KKP, adalah terumbu karang yang kondisinya dapat dinilai rusak dan atau sangat rusak.
Syamsul juga memaparkan, pihaknya juga telah diserahi secara bertahap mengenai sejumlah kawasan taman nasional laut yang pengelolaannya diberikan dari Kementerian Kehutanan kepada KKP.
Ia mengemukakan, salah satu cara untuk memperbaiki kondisi karang di Indonesia adalah dengan melakukan pengelolaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
Pengelolaan yang berkelanjutan itu, ujar dia, harus memperhatikan berbagai aspek yaitu aspek ekonomi, ekologi, dan juga sosial-budaya.
Selain itu, menurut Syamsul, tindakan yang sangat penting adalah dengan memberdayakan masyarakat antara lain dengan melakukan pendidikan dan pelatihan berupa kampanye publik.
"Karang kita yang kondisinya baik sekitar 30 persen," kata Syamsul Maarif dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) KKP dan World Wildlife Fund (WWF) Indonesia di Kantor KKP, Jakarta, Senin (23/8) lalu.
Ia juga menuturkan, selain 30 persen karang yang berkondisi baik, jumlah karang yang kondisinya sangat baik adalah jauh lebih kecil lagi hanya sekitar enam persen.
Sedangkan sisanya, lanjut Sekjen KKP, adalah terumbu karang yang kondisinya dapat dinilai rusak dan atau sangat rusak.
Syamsul juga memaparkan, pihaknya juga telah diserahi secara bertahap mengenai sejumlah kawasan taman nasional laut yang pengelolaannya diberikan dari Kementerian Kehutanan kepada KKP.
Ia mengemukakan, salah satu cara untuk memperbaiki kondisi karang di Indonesia adalah dengan melakukan pengelolaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
Pengelolaan yang berkelanjutan itu, ujar dia, harus memperhatikan berbagai aspek yaitu aspek ekonomi, ekologi, dan juga sosial-budaya.
Selain itu, menurut Syamsul, tindakan yang sangat penting adalah dengan memberdayakan masyarakat antara lain dengan melakukan pendidikan dan pelatihan berupa kampanye publik.
Selasa, 14 September 2010
Pencemaran Limbah pada Air Sungai dan Laut
 |
Padahal yang kita tahu, limbah tersebut merupakan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), seperti yang disebutkan pada UUPPLH No.32 Tahun 2009 pasal 1 angka 21 disebutkan bahwa “Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat menjadi B3 adalah zat, energy, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.” Biasanya limbah B3 mengandung merkuri, plumbum dan coopper yang semuanya itu berbahaya bagi tubuh manusia.
Sedangkan kenyataannya disisi lain masyarakat banyak yang menggunakan air sungai untuk mandi, minum (yang sebelumnya direbus terlebih dahulu), buang air besar, mencuci, dan semua kegiatan itu dilakukan pada satu tempat. Jadi dapat kita bayangkan seberapa kotornya sungai yang sebelumnya sudah tercemari oleh limbah pabrik dan sampah-sampah ditambah lagi dengan limbah manusia.
Pencemaran air dapat terjadi di sungai dan di laut. Pencemaran air sungai lebih didominasi oleh limbah pabrik dan sampah. Seperti contohnya di kota Bandung. Hampir semua sungai yang terdapat di kota Bandung tercemari oleh limbah pabrik dan sampah-sampah. Pencemaran sungai yang terjadi di Bandung diakibatkan oleh meningkatnya jumlah penduduk otomatis sampah yang dihasilkan semakin banyak. Selain karna meningkatnya jumlah sampah juga dikarenakan semakin sempitnya bahkan semakin berkurangnya lahan untuk digunakan sebagai tempat pembuangan sampah. Tidak adanya lahan disebabkan oleh lahan yang ada digunakan dan dimanfaatkan sebagai areal perumahan maupun gedung-gedung sehingga banyak sampah yang sengaja dibuang di sungai dan tertimbun di dalam tanah. Selain karena sampah, air sungai tercemar juga disebabkan oleh limbah-limbah pabrik yang sengaja dibuang ke perairan khususnya sungai.
Selain itu, pencemaran air juga terjadi di laut. Apabila membahas tentang pencemaran air di laut banyak limbah pabrik yang dibuang begitu saja di laut. Padahal di dalam laut banyak sekali ekosistem yang seharusnya patut untuk jaga. Dampak yang diakibatkan oleh pencemaran limbah tersebut yaitu warna air laut manjadi gelap, banyak ikan-ikan yang mati, selain ikan kandungan limbah juga berdampak pada makhluk hidup yang ada di laut.

Pada gambar tersebut dapat kita lihat warna air laut hitam pekat dan juga mengandung minyak. Pada gambar tersebut juga terlihat ikan yang mati karena teracuni oleh bahan kimia yang terkandung dalam limbah. Apabila hal ini tidak mendapat perhatian dan tetap saja dibiarkan maka semakin lama ekosistem laut akan musnah.
Sebagai contoh kasus Minamata. Pada kasus tersebut pencemaran air laut terjadi dikarenakan limbah-limbah pabrik yang dibuang ke laut. Padahal limbah tersebut mangandung B3 salah satunya bahan kimia merkuri. Merkuri sangat berbahaya, karena dapat mengakibatkan kematian. Banyak penduduk sekiatar yang mati akibat kandungan limbah tersebut.
Penyelesaiannya tidak hanya dari pemerintah tetapi juga dari kesadaran tiap individu. Pemerintah memang berkewajiban untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Karena Negara memiliki tanggung jawab menurut asas UUPPLH (Pasal 2) antara lain:
a. Negara manjamin pemanfaatan SDA akan mamberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun mendatang.
b. Negara menjamin hak warga Negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan SDA yang menimbulkan pencemaran dan/ kerusakan lingkungan hidup.
Selain itu pemerintah juga berkewajiban untuk memberikan sanksi-sanksi tegas kepada pabrik-pabrik yang dangan sengaja membuang limbah-limbah pabriknya di perairan lepas karena apabila tetap dibiarkan maka dampaknya akan semakin parah terhadap lingkungan.
Kesadaran individu juga sangat diperlukan untuk kelestarian lingkungan karena dengan suatu kesadaran maka akan mengurangi kerusakan lingkungan mulai dari tindakan yang kecil sampai yang berpengaruh besar.
Selain pemerintah yang bertanggung jawab, pihak pencemar juga bertanggungjawab dalam masalah tersebut, bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/ kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/ kerusakan wajib menanggung biaya pemulihan.
Apabila dikaitkan lagi dengan asas UUPPLH (Pasal 2) dalam bentuk partisipatifnya bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.
Sedangkan dalam asas ekoregion disebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik SDA, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal. Dengan diperhatikannya karakteristik-karakteristik tersebut maka akan mengurangi terjadinya kerusakan lingkungan.
Pencemaran air juga dapat digolongkan sebagai pencemaran lingkungan hidup. Maka setiap lingkungan hidup sangat diperlukan adanya perlindungan dan pengelolaan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdapat pada tujuan UUPPLH (Pasal 3) yaitu:
1. Melindungi wilayah kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia.
3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa mendatang.
7. Menjamin pemenuhan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
10. Mengantisispasi isu lingkungan global.
Dengan makin banyaknya kasus pencemaran lingkungan terutama pencemaran air seharusnya ini dapat menjadi “PR” bagi pemerintah dan juga seluruh masyarakat agar dapat menciptakan lingkungan yang sehat, bersih dan tidak berdampak buruk bagi kehidupan manusia.
LPM Pro Justicia
Sabtu, 11 September 2010
Puspitek Kembangkan Teknologi Tenaga Listrik dari Sampah
 setumpuk sampah organik (foto: jawapos)
setumpuk sampah organik (foto: jawapos)Tangerang - Teknologi pengolahan sampah dengan cara menciptakan sampah organik menjadi tenaga listrik, kini tengah dikembangkan oleh Pusat Penelitian Ilmu dan Teknologi (Puspitek) Serpong. Kepala Puspitek Serpong, Jemi Ruslan, mengatakan temuan para ahli di lembaganya itu siap digunakan oleh stakeholder yang membutuhkan. "Ini yang nantinya bisa diproduksi secara massal," katanya di sela Pameran Teknologi di Pamulang, hari Selasa, 7 Juni 2010.
Jemi mengatakan, teknologi mengubah sampah menjadi tenaga listrik itu sangat sederhana dan efektif dalam menangani sampah dan mengatasi krisis energi listrik di Indonesia. Prinsip kerjanya, kata dia, satu buah genset 1.000 watt dapat digerakkan dengan setumpuk sampah organik.
Dalam teknologi ini, sampah organik dimasukkan ke tabung reaktor yang tersambung dengan genset. Sampah yang telah diproses dalam reaktor akan mengeluarkan gas metana, yang kemudian diubah menjadi tenaga listrik untuk mengoperasikan genset. "Listrik yang dihasilkan cukup untuk menerangi satu kompleks rukun warga," tuturnya.
Teknologi ini, kata Jemi, sangat tepat untuk kalangan komunitas kecil seperti RT dan RW. Jika dikembangkan terus, masyarakat bisa dilatih untuk memanfaatkan teknologi itu sebagai alternatif mencari energi listrik
Jumat, 03 September 2010
Pemerintah Undang Swasta Terlibat Pengolahan Sampah
Pemerintah mengundang partisipasi swasta dalam bisnis pengelolaan sampah di Indonesia melalui skema Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism/CDM). Menurut Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto proyek CDM tidak saja sebagai upaya upaya mengurangi emisi gas rumah kaca tetapi juga dapat menjadi alternatif tambahan bagi pendanaan untuk mendukung peningkatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di kota.
Pernyataan tersebut disampaikan Djoko Kirmanto saat membuka Seminar Mekanisme Pembangunan Bersih Sektor Persampahan di Jakarta, Rabu (25/2). Seminar tersebut merupakan hasil kerjasama Departemen PU dengan Departemen Tanah, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang.
Menteri PU menuturkan, jumlah sampah yang dibuang ke TPA setiap harinya di kota-kota besar Indonesia mencapai 500 - 6.000 ton. Hampir seluruh TPA masih dioperasikan secara terbuka atau open dumping, hanya beberapa saja yang telah menerapkan controlled landfill. Namun belum ada yang mengembangkan sanitary landfill.
Pengelolaan sampah sistem open dumping menimbulkan pencemaran udara akibat emisi gas methane yang dihasilkan timbunan sampah di TPA. Terkait dengan mitigasi terhadap emisi gas tersebut, di kota-kota besar penanganan gas landfill dikembangkan kearah waste to energy (WTE) .
.
 .
. Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan sampah di TPA, kegiatan penanganan gas melalui skema CDM merupakan peluang potensial yang dapat dimanfaatkan pemerintah kabupaten/kota bekerjasama dengan swasta. Dengan keterlibatan swasta, maka dapat membantu dalam biaya operasional TPA. Saat ini biaya operasionalnya senilai Rp 50.000 – Rp 100.000 per ton sampah.
Djoko Kirmanto mengatakan selama ini biaya investasi dibidang ini cukup tinggi untuk ia mendesak kepada pelaku swasta bisa memanfaatkan peluang tersebut. Menurutnya investasi di pengelohan sampah cukup menguntungkan artinya investor tidak perlu khawatir mengenai potensi keuntungan yang bisa diperoleh. Meskipun risiko resistensi terhadap pembangunan TPA saat ini masih cukup tinggi terhadap masyarakat.
Saat ini ada lima pemerintah kota yang telah bekerjasama dengan swasta dalam pelaksanaan CDM yaitu TPA Batulayang, Pontianak, Kalimantan Barat, TPA Sumur Batu, Bekasi Jawa Barat, TPA Suwung, Denpasar, Bali, TPA Sukowinatan, Palembang dan TPA Tamangapa, Makassar, Sulawesi Selatan.
Menteri PU mencontohkan salah satu proyek CDM yang berhasil ialah TPA Suwung, Denpasar. Meski belum rampung 100 persen, namun saat ini telah mampu menghasilkan listrik yang berhasil dijual seharga Rp 600 per kwh. Dengan mengolah sampah 500 ton per hari yang memiliki daya 10 megawatt.
Sementara itu Direktur Jenderal Cipta Karya, Budi Yuwono mengatakan, masuknya swasta dalam pengolahan sampah tergantung kepada pasar dalam hal ini peran pemerintah kota dan kabupaten menciptakan iklim kondusif.
 Budi mengatakan, dalam pengolahan sampah sampai saat ini belum ada yang masuk sekala ekonomi seperti sebagai pembangkit listrik seharusnya dapat mencapai 10 sampai 20 megawatt tergantung tersedianya sampah setiap hari.
Budi mengatakan, dalam pengolahan sampah sampai saat ini belum ada yang masuk sekala ekonomi seperti sebagai pembangkit listrik seharusnya dapat mencapai 10 sampai 20 megawatt tergantung tersedianya sampah setiap hari.
Seperti di Bali saat ini baru menghasilkan 3 megawatt atau baru 30 persen, saat ini sudah ada rencana alokasi dana 70 juta dolar AS dari Australia untuk penanganan sampah.
”Ada dua pilihan dalam mengelola sampah membuat sama sekali baru, atau menyempurnakan lokasi yang sudah tersedia,” sebut Budi Yuwono.
Selain listrik, sampah juga dapat menghasilkan kompos (pupuk), setidaknya investasi awal berkapasitas 500 ton per hari membutuhkan dana 20 juta dolar AS tergantung peruntukan.
 Budi mengatakan, dalam pengolahan sampah sampai saat ini belum ada yang masuk sekala ekonomi seperti sebagai pembangkit listrik seharusnya dapat mencapai 10 sampai 20 megawatt tergantung tersedianya sampah setiap hari.
Budi mengatakan, dalam pengolahan sampah sampai saat ini belum ada yang masuk sekala ekonomi seperti sebagai pembangkit listrik seharusnya dapat mencapai 10 sampai 20 megawatt tergantung tersedianya sampah setiap hari.Seperti di Bali saat ini baru menghasilkan 3 megawatt atau baru 30 persen, saat ini sudah ada rencana alokasi dana 70 juta dolar AS dari Australia untuk penanganan sampah.
”Ada dua pilihan dalam mengelola sampah membuat sama sekali baru, atau menyempurnakan lokasi yang sudah tersedia,” sebut Budi Yuwono.
Selain listrik, sampah juga dapat menghasilkan kompos (pupuk), setidaknya investasi awal berkapasitas 500 ton per hari membutuhkan dana 20 juta dolar AS tergantung peruntukan.
Untuk lebih mengembangkan pengolahan sampah berbasis CDM, Djoko Kirmanto mengaku terbantu dengan adanya bantuan berupa berbagi pengalaman dan pengetahuan dari pemerintah Jepang. Dalam teknologi pengolahan gas bidang persampahan, Jepang memang telah lebih maju dibandingkan Indonesia.

Wakil Menteri Tanah, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang Seigo Sakaki mengungkapkan, penerapan CDM bidang persampahan di negaranya berkontribusi terhadap penurunan emisi gas sebesar 1,6 persen. Sesuai kesepakatan Protokol Kyoto, Jepang menargetkan penurunan emisi gas sebanyak 7 persen.
“Selain transfer knowledge, Jepang juga membantu Indonesia melalui pengiriman tenaga ahli dan grant (hibah-red),” ucap Seigo Sakaki. (rnd)
Informasi Tentang Tekhnol0gi Pengolahan Sampah Perkotaan

“Kunjungan ini adalah bertujuan untuk menjembatani kesenjangan informasi tentang teknologi pengelolaan sampah perkotaan terkini. Dengan itu maka diharapkan, dapat terjalin tukar informasi antara para peneliti di BPPT dengan kalangan akademisi”, kata Ketua Rombongan Studi Ekskursi program Magister Sistem Teknik UGM, Muhammad Sulaiman, dalam kunjungannya ke Pusat Teknologi Lingkungan (PTL) BPPT, Senin (7/06).
Lebih lanjut Ia mengatakan, kunjungan dengan jumlah peserta sebanyak 53 orang tersebut, juga ditujukan agar kalangan akademisi dapat secara langsung mengetahui secara nyata prospek teknologi pengelolaan sampah dan penanganan masalah limbah perkotaan.
Kepala Bidang Pengelolaan Limbah PTL BPPT, Arie Herlambang, berkesempatan untuk menjelaskan tentang profil dari BPPT, khususnya tentang kegiatan yang dilakukan di PTL. Selain itu, Arie juga sedikit memaparkan tentang capaian-capaian teknologi yang telah berhasil dikembangkan oleh tim PTL berkaitan dengan penanganan limbah perkotaan.
Dalam acara tersebut, disampaikan juga kegiatan-kegiatan terkini dari PTL terkait dengan kerjasama yang dilakukan antara BPPT dengan Kementerian PU dan Pemprov Bali, di Bangli. Pembangunan pilot plant Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di Bangli nantinya akan menggunakan sistem RSL (Reusable Sanitari LandfillI)-Wet Cell dan Enhanced Conventional Sanitary Landfill (ECSL)-Dry Cell.
Rencananya, hasil ujicoba pilot plant tersebut akan dimanfaatkan untuk menyusun definisi serta standar teknis baru untuk rehabilitasi TPA Open Dumping, pembangunan dan pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir/TPA baru di Indonesia.
Terkait dengan UU 18/2008 tentang persampahan, aspek akan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang ingin mengeksplorasi teknologi pengolahan sampah sangatlah penting. Hal tersebut dimaksudkan agar program rehabilitasi lokasi TPA Open Dumping, dapat berjalan lancar.
Diharapkan dengan penerapan teknologi RSL untuk rehabilitasi TPA-Open Dumping, investasi dan biaya operasi TPA dapat dijangkau pihak pemerintah daerah, menunjang kegiatan 3R oleh masyarakat agar dapat berlangsung berkesinambungan, segera siap memenuhi amanah UU18/2008 tentang pengelolaan sampah.
Hadir dalam acara kunjungan, Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan PTL BPPT, Joko PS, serta beberapa perekayasa dari PTL seperti Nusa Idaman Said, Djoko Heru Martono, Henky Sutanto, Suprapto dan Sriwahyono. (ADS/HBHS-ptl/YRA-humas)
Kepala Bidang Pengelolaan Limbah PTL BPPT, Arie Herlambang, berkesempatan untuk menjelaskan tentang profil dari BPPT, khususnya tentang kegiatan yang dilakukan di PTL. Selain itu, Arie juga sedikit memaparkan tentang capaian-capaian teknologi yang telah berhasil dikembangkan oleh tim PTL berkaitan dengan penanganan limbah perkotaan.
Dalam acara tersebut, disampaikan juga kegiatan-kegiatan terkini dari PTL terkait dengan kerjasama yang dilakukan antara BPPT dengan Kementerian PU dan Pemprov Bali, di Bangli. Pembangunan pilot plant Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di Bangli nantinya akan menggunakan sistem RSL (Reusable Sanitari LandfillI)-Wet Cell dan Enhanced Conventional Sanitary Landfill (ECSL)-Dry Cell.
Rencananya, hasil ujicoba pilot plant tersebut akan dimanfaatkan untuk menyusun definisi serta standar teknis baru untuk rehabilitasi TPA Open Dumping, pembangunan dan pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir/TPA baru di Indonesia.
Terkait dengan UU 18/2008 tentang persampahan, aspek akan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang ingin mengeksplorasi teknologi pengolahan sampah sangatlah penting. Hal tersebut dimaksudkan agar program rehabilitasi lokasi TPA Open Dumping, dapat berjalan lancar.
Diharapkan dengan penerapan teknologi RSL untuk rehabilitasi TPA-Open Dumping, investasi dan biaya operasi TPA dapat dijangkau pihak pemerintah daerah, menunjang kegiatan 3R oleh masyarakat agar dapat berlangsung berkesinambungan, segera siap memenuhi amanah UU18/2008 tentang pengelolaan sampah.
Hadir dalam acara kunjungan, Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan PTL BPPT, Joko PS, serta beberapa perekayasa dari PTL seperti Nusa Idaman Said, Djoko Heru Martono, Henky Sutanto, Suprapto dan Sriwahyono. (ADS/HBHS-ptl/YRA-humas)
Kamis, 02 September 2010
TEKNOLOGI PENGOLAHAN SAMPAH KOTA DENGAN SISTEM SEL TIDAK TIMBULKAN BAU
Jakarta, 25/8/2010 (Kominfo-Newsroom) Hasil penelitian kerjasamaBadan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dengan PT. NavigatOrganic Energy Indonesia (NOEI) terhadap pengolahan sampahperkotaan dengan sistem sel basah dan kering terbukti tidakmenimbulkan bau yang menyengat dan sanitasi lingkungannya dapatdikendalikan dengan baik.
Disamping itu, dari pengolahan sampah perkotaan dengan sistemsel tersebut, juga dapat memproduksi gas metana, kata Kepala BidangTeknologi Pengendalian Pencemaran Lingkungan, BPPT, Dr. Ir. ArieHerlambang, MS pada siaran iptek voice di Kemristek, Rabu(25/8).
Menurutnya, penelitian tersebut dilakukan mulai 2009, berlokasidi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung, Denpasar,
Sedangkan potensi sampai wilayah Sarbagita sekitar 800 ton perhari, dan diprediksi dapat menghasilkan listrik 9,6 megawatt. Namunsaat ini, pemasokan sampah baru mencapai 350-500 ton per hari. Saatpercobaan dilakukan terdapat 4 mesin dengan kapasitas masing-masing1 megawatt, namun baru bisa dihidupkan satu mesin dengan produksilistrik 470 kilowatt.
TPA sampah sistem sel tersebut mempunyai kapasitas 12.000 m3sampah dan diprediksi dapat memproduksi listrik sekitar 364 kw.Setiap sel sampah mempunyai dimensi lebar 20 meter, panjang 28meter, dan tinggi 12 meter. Dinding terbuat dari konstruksi betonbertulang, dan bagian atas tertutup dengan menggunakan terpalplastik.
Dibagian bawah sel terdapat saluran lindi yang dikumpulkankearah depan dengan kemiringan 5 persen dimasukkan ke dalam pipapengumpul. Sistem dilengkapi dengan pipa untuk melakukan sirkulasiair.
Sumur pengumpul gas dengan diameter 6 ditanam setiap jarak 5meter dibagian tengah sampai pada kedalaman 12 meter. Gas darisetiap sumur dikumpulkan dengan pipa fleksibel dan dialirkankebagian depan sel, dan siap dihisap gasnya.
Penghisapan di pusat pompa dilakukan sampai pada tekanan -50 mb,namun dikontrol dengan gas oksigen yang terhisap tidak boleh lebihdari 6 persen.
Ia mengungkapkan, tujuan dari penelitian tersebut adalah untukmelakukan pengukuran gas di TPA Sistem Sel basah dan kering diSuwung, Denpasar,
Termasuk, sebagai masukkan bagi usulan kebijakan pengelolasampah
Selasa, 30 Maret 2010
ANTARA AKU DAN HARIMAU ITU…
"Extination is forever", begitulah satu petuah bijak, apapun yang menyangkut kepunahah adalah abadi. Manghindarinya, karna kita tak ingin anak cucu kita nanti hanya mendengar terompet kawanan gajah dari cerita saja. Mereka harus jadi saksi langsung sepak terjang "si Belang" sang raja rimba. Aku pun yakin mereka akan bersuka melihat tingkah pola pemalunya si endut bercula alias badak. Namun pertanda kepunahan itu ada dan sangat jelas di mataku sekarang. Gading culah dan kulit "si Belang" yang tak terharga nilai dan sudah menjadi kepentingan heritage di negri ini, sudah di sulap menjadi rupiah oleh segelintir durjana. Belum sepenuhnya kehidupan manusia menyatu, meretas dengan alam. Arus kerusakan terlalu kuat untuk di bendung membuat hatiku separti tertikam.
Pun mendapati berita ini hari. Bahkan segelas kopi kental kas kota ini yang seharusnya membuat gairah roda-roda hariku kini tak lagi nikmat bahkan tuk sakedar tuk di cicip. Ketika pai rokok ku membakar sisa batang yang tersisa, nikmatpun tak lagi. Aku kasih tajuk ini hari sebagai 'Oktober kelabu', ketika anaku lahir telah menyandamg duka, kawan gajah di Cagul mati secara mengenaskan dan misterius. Beberapa temuan racun mematikan, maka aku terujung pada kesimpulan, kawanan gajah malang itu di binasahkan. Bagi para durjana, tak lebih dari hama perusak tanaman. Keberadanya berarti malapetaka kerugian. Tak selang dari seminggu, masyarakat di hebohkan kembali konflik tiga harimau yang menyerang pekon tampang tua "si Belang" menjemput ajalnya pada satu pertikaian yang tak berimbang. Di Koran di sebutkan 22 ekor kambing dan 10 ekor ayam. Sedangkan matinya si belang di anggap lumrah bahkan tak banyak menyisakan luka. Bahkan se cuil pun tidak, malah Nampak raut wajah serasa menyiratkan kepuasan.
Aku terus berfikir, pada bagian mana harus kuselipkan sisi cerita tuk anakku sepuluh tahun mendatang bahwa "si belang" ke pemukiman hanyalah sebuah keterpaksaan karena mangsanya di rimba telah banyak di lenyapkan kaum serakah kota. Harimau menyerang manusia, dan manusia menyerang harimau. Aku semakin di liputi kecemasan. Upaya penyelamatan ini tak sepadan dan terasa sia-sia, bagai mana perang harus di benturkan denga laras panjang. Meradang sekujur tubuh melihat sebongkah daging besar yang membujur kaku. Berserakan puluhan mayat gajah tak bergading lagi. Mungkin inihari. Musuh sedang berpesta layaknya belatung menggerogoti bangkai-bangkai ini tak jauh dari radius TKP, seekor badak masih terjerat saling terkapar mengenaskan tenpa kepala tertebas chain saw para durjana. Jika begini maka yang biasa di lakukan hanya menghitung dan menghitung hari bahwa kenyataan tak terelakan: jumlahnya kini mulai berkurang. Mereka berhasil menikam perut rimba ini dari segala penjuru tanpa ampun.
Secara yang ku tunggu mendekati harapan nyata. Tebaran cahaya semalam kala purnama nampak pesona menembus tetinggian pohon rimba. Dua durjana dan satu penadah dari berita yang mambuat api semangat yang lama padam kembali berkobar setelah puluh tahun lamanya di liputi dahaga akan itu. Di hadapan siaran live salah satu stasiun televisi nasional aku bercerita lantang: akulah ''si belang" akulah gajah itu, dan akulah badak dari anak-anakku.
Ini barulah awal dari suatu perang. Aku berjuang untuk cerita anak-anakku kedepan. Sebab musuh utama yang menjadi kepunanahan adalah cukong. Mereka belum sama sekali tersentuh vonis memang telah di jatuhkan, tapi belum pada saran bidik yang sesungguhnya. Orang yang di hadapan ku terpekur di kursi pesakitan sebagai terdakwa dan betapa ku ingin meledakan kapalanya dangan panah namun hanyalah sama-sama korban sebagai mana "si belang" badak ataupun kawanan gajah yang telah mereka lukai. Satu kata saja, merekan di hadapkan persoalan ketak berdayaan jeratan hidup. Anak-anakku pasti penuh caci maki mengetahui berapa imbal balik yang di bayarkan atas perburuan gading, kulit, "si belang" atau pun cula. Sama sekali mereka tidak di untungkan di lingkaran bisnis ini. Toh bagaimanapun mereka layak mendapatkan ganjaran karena memang punya andil.' Jadi, ini belumlah selesai",kataku dalih mereka keluar dari jeratan hidup dengan cara seperti itu haruslah di pupus. Aku masih di liputi kecemasan.
Tibalah kami di petok 50, ketika bersamaan patroliku di kejutkan bayangan berkelebatan di kejauhan melompat dan mendedadak berhenti di tengah jalan. Lampu mobil sengaja kunyalakan namunt idak bias memastikan hewan atau mahluk apakah itu. Yah dugaan kami benar, kami di hadang "si belang". Aku menghantikan laju roda tepat tak lebih jarak 5 meter. Di ujung jalan penuh lobang membelah bukit kali pertama dalam sejarahku bersanding "si belang" dalam jarak sedakat ini. Sorot mata begitu tajam mencerang, namun pembawaannya begitu teduh. "kita coba turun dari mobil saja pak!",ucap ijal pelan. 'yah, kita ambil resiko, 'kawan kita' sepertinya tak ada tanda-tanda akan menyerang", sahutku.
Senjatanya pak!, kembali ijal mengingatkanku. "betul jal, sebaknya kita tak usah bawa senjata tinggal saja di mobil!" bergegas walau rasa was-was sedikit menghanyut di dada. Sekelilingku terlihat lebih angker, bulu kuduk merinding dan sedikit mengusikku. Hal ini tak terduga sama sekali. Aku dan ijal terus berkomunikasi lewat isyarat. Untuk sesaat ingatanku kembali tertuju pada saat pertama kali menginjakan kaki di belantara ini. Aku berkirim kabar pada adinda kekasihku. Mungkin adinda satu-satu yang mempercayai.
Adinda………. Mungkin tak ada yang percaya bila kisah ini kuceritakan, sedang kisah ini amatlah indah…. Manakala aku tersesat…. Kali pertama aku mengakrabi hutan ini, belum sepenuhnya jalan setapak kukenali dengan baik. Aku berjalan lama hari itu, hampir separo lebih. Dan aku tak tahu andinda……. Sama sekali tak sadar sama sekali aku tak sadar saat sore beranjak menapaki malam, jalanku telah salah arah malah menghantarkanku ke tanjakan dan berujung berbatu…. Dan katika telah sadar…. Aku sungguh di liputi kacamasan memikirkanmu andinda. Cuaca begitu angker hinggaku tak menemukan jalan ke perkampungan. Jika badai ini datang, maka mampuslah aku sayangku. Aku akan mati di sini sebelum aku bisa berbuat untuk rimba ini. Andinda, aku tak paham misteri rimba ini, namun kau harus kukabari….. bahwa jejak basah si belang telah menyalamatkanku begitu aku melihatnya, hatiku di penuhi semangt '45 dengan sisa tenaga, aku ikuti jejak si belang menghilang pada jarak 20 meter dari perkampumgan……… aku selamat sayangku dan betapa terharunya aku. Yours forever (16 november 2000, lampung)
Dan pada detik ini mungkin si belang yang telah manuntunku itu. Maka aku menyapa sebisaku. Pak, sepertinya 'kawan kita' ingin menunjukan sesuatu," "yah kau juga berfikir sama jal. Apa gerangan terjadi?" ucapku lirih rasa was-was yang menghantui beberapa saat lalu perlahan lenyap, aku terhenyak sesaat melihat "si belang" mendadak meloncak lari menuju jalan setapak hutan, sebelum lebih jauh menyusuri, si belang mengaum keras, memperlihatkan taring ajamnya dan kembali menoleh arahku. Pasti ada misteri di balik ini jal. Ayo kita ikuti!" gerakanku sengaja kubuat lebih gasit selayaknya sepasang harimau sedang bercengkarama, menari di sepanjang pegunugan. Si belang terus berlari menyusuri bukit masih dalam jalan setapak, manuju hulu air-ke kali yang bening si belang menghantikan langkah persis di dekat kubangan badak. Sebelum sempat berfikir, aku di kejutkan suara keras ijal yang berdiri tepat di sebelah kiriku. "lihat itu pak!" benar saja, sosok tubuh tersungkur meski masih samar dalam pandanganku, bergegas kami mendatangi. "jonfa?!!" kanapa kau!!??" ijal spontan mendekap, melihat tubuh sohib karibnya bersimbah darah, belepotan lumpur di sekujur tubuh dan seragam lapangan jonfa. Sama sekali aku tak menyangka, rupanya inilah misteri itu. Aku tak melihat kemana lagi si belang itu pergi. "oh Tuhan, teman seperjuanganku sekarat." Dengan setengah di paksa Jonfa mencoba tersenyum lebar menyambut kedatanganku dan ijal. "jangan bicara dulu kau akan selamat, kami telah bersamamu, kau akan selamat Jonfa!!, ucapku lirih "Tt….tt…tidak pak. Durjana keparat itu kabur sebelumku ledakan kepalanya. Mereka telah membrondong gajah tunggal dangan lonco. Di antara kami sempat kontak senjata, namun dari arah belakang sekejap sebetan belalai gajah itu melumpuhkanku. Aku yakin gajah itu tidak sengaja malukaiku"
Ijal memeriksa sekeliling, jelas sekali kodisi sekitar acak-acakan layaknya medan pertempuran. Beberapa pohon besar tumbang, sungguh pemandangan dari amarah yang dahsyat. Aku dan ijal dan dalam perjuangan, menggotong tubuh Jonfa menapaki jalan rimba menuju mobil. Upaya tak kenal lelah dan saling menyemangati. Tangis ku tahan melihat Jonfa berjuang menahan perih mendalam. Aku yakin ada yang pecah dalam perut Jonfa, persis pecahnya perut rimba ini. Kau akan selamat kawan, selepas tanjakan ini''ucap Ijal mengiba.
Setiba di mobil patroli ijal mencoba kontak radio pos pengamanan terdekat. Namun gagal. Aku sendiri bergegas memacu mobil patroli debar mengikuti alur tikungan-tikungan tajam. Persetan hari mulai gelap. Dalam satu kedekatanku dengan-nya, aku berharap satu keajaiban satu keajaiban muncul lagi, seprti kisah seperti kisah tersesatku dan jejak si belang. "Jal' kau kenapa??!", tanyaku kaget, melirik Ijal yang mukanya telah banjir air mata. Aku semakin bingung manakala Ijal tak lagi berucap. "Jal, kau kenapa??, tanyaku sekali lagi. "kita manusia pak lemah tak berdaya, ini sungguh perjuangan terbaik kawanku Jonfa!" aku kaget dan tak sanggup menerima kenyataan, refleku menginjak pedal rem. Aku merinding kukira aku akan sanggup menerima dan memupus tangan malaikat ajal. Cerita 'Okotober kelabu' lengkap sudah, langit pun tertutup mendung mengiringi kepergian Jonfa, pertanda duka rimba, doa tulus kami kawan, kau meninggalkan kami dalam seragam kebesaranmu,"
Sesaat telah aku tabur bunga di pemakaman Jonfa, aku melihat gajah tunggal itu, aku menjadi saksi kedatangannyna di makam Jonfa. Aku menjadi saksi linangan air matanya. Dan aku menjadi saksi pula atas sepasang gading dikuburkan di dekat zenajah Jonfa. Perang belum selesai. Manakal amarah rimba dan serakahnya orang kota belum memudar.. ya perang ini benar benar belum selesai...............
Langganan:
Postingan (Atom)